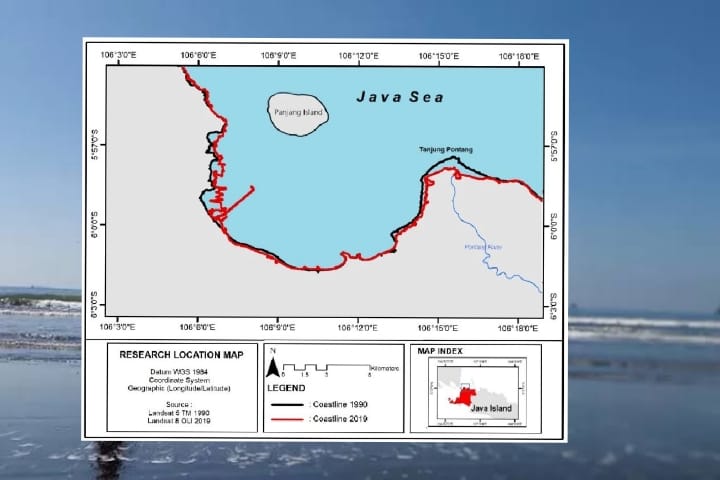Mengembalikan Daulat Maluku Sebagai Negeri Maritim (Bag-1)
by Dr. Saidin Ernas
Tahun 2017 silam, saya mendapatkan kehormatan untuk menghadiri sebuah Focus Group Discussion (FGD) tentang upaya membangun dunia kemaritiman di Maluku. Diskusi tersebut dihadiri Gubernur Maluku, Wakil Ketua DPD RI Ibu Ratu Hemas beserta empat anggota DPD RI asal Maluku. Selain itu, hadir juga sejumlah ahli politik, ekonomi, dan kebudayaan. Tidak ketinggalan para ahli kelautan dari Universitas Pattimura Ambon.
Beberapa guru besar kelautan dari Universitas Pattimura mempresentasikan potensi ekonomi kelautan di Maluku. Potensi yang bila dikonversi kedalam rupiah, maka nilai keekonomiannya diyakini mampu menopang kesejahteraan seluruh rakyat Maluku. Bahkan dapat menyumbang secara siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Melalui tulisan ini saya tidak akan menceritakan tentang nilai keekonomian atau angka-angka ekonomi kelautan yang fantastis itu. Saya justru tertarik dengan kritik seorang anggota DPD RI asal Maluku yang juga seorang guru besar di sebuah universitas di Jakarta. Anggota DPD itu menyangsikan hipotesis bahwa masyarakat Maluku adalah kelompok masyarakat yang memiliki mentalitas dan karakter yang dibutuhkan sebagai bangsa pelaut yang Tangguh.
Bangsa pelaut tangguh sebagaimana yang jamak ditemukan pada para pelaut Mandar dan Bajo di Sulawesi Selatan atau nelayan-nelayan Banyuwangi dan Madura dari Jawa Timur. Nelayan-nelayan Maluku hanya berlayar di sekitar laut Maluku. Itupun sekedar menjalani aktifitas kenelayanan secara temporal. Sebab umumnya nelayan Maluku mengandalkan pendapatannya dari aktifitas pertanian dan perkebunan.
Bila dipahami secara sepintas, apa yang dikatakan senator asal Maluku tersebut pasti dapat dibenarkan. Sebab pada realitasnya para nelayan di Maluku bukanlah pelaut dan nelayan tangguh. Bukan nelayan yang berani menantang samudra hingga batas terjauh. Para nelayan Maluku juga tidak memiliki budaya terkait penguasaan teknologi kenelayanan, seperti perkapalan yang dapat digunakan untuk menopang aktifitasnya.
Perahu-perahu di Maluku, seperti kora-kora, koli-koli atau giuk adalah perahu tradisional yang sulit melakukan pelayaran jarak jauh. Namun bagi semua kesan tersebut adalah kesimpulan yang masih dangkal dan perlu diklarifikasi lebih seksama. Apakah benar masyarakat Maluku adalah sebuah komunitas kepulauan yang telah melupakan alam kelautan dan pesisir yang mengitarinya? Sehingga nelayan Maluku tidak memiliki etos sebagai bangsa maritim yang patut dibanggakan lagi? Ataukah kondisi tersebut merupakan sebuah realitas yang tercipta melalaui berbagai bentuk politisasi dan rekayasa sosial yang telah berlangsung lama.
Tiga fakta kehancuran bila kita membaca sejumlah data sejarah. Secara historis aktifitas kelautan di Maluku bukan sekedar aktifitas kenelayanan yang rapuh. Tetapi lebih dari itu berkaitan dengan fakta kehancuran kebudayaan dari suatu masyarakat maritim yang pernah berjaya. Masyarakat Maluku bukanlah kamunitas yang tidak mencintai laut, ombak, ikan, batu, karang dan angin yang terhampar di depan matanya.
Masyarakat Maluku dulu adalah pelaut-pelaut yang tangguh. Peluat yang menjajah lintas samudera yang disegani kawan dan lawan. Pelaut-pelaut Maluku adalah pedagang-pedagang kaya yang pernah menguasai jalur perdagangan rempah dan hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi. Mereka pernah berjaya dan memeriahkan aktifitas perdagangan dunia pada abad 16 hingga abaad 18, yang berpusat di perairan Maluku.
Harus diakui, dunia kemaritiman Maluku mengalami kemunduran, kehancuran dan kejatuhan secara perlahan-lahan. Setidaknya ada tiga situasi yang menyumbang kepada realitas tersebut. Baik itu berupa tragedi yang dapat dilacak sejak masa lalu, maupun dinamika sosial politik kontemporer sebagai akibat kekeliruan kebijakan pembangunan pada masa Indonesia Moderen.
Fase pertama dari kehacuran peradaban maritim Maluku itu bisa dilacak pada era kolonialisme. Sejarawan LIPI Muridan Widjoyo mencatat bahwa masyarakat Maluku adalah pelaut-pelaut tangguh yang biasa melayari nusantara, bahkan hingga ke India. Mereka menjalankan aktifitas perdagangan rempah-rempah secara independen dengan berbagai bangsa. Catatan Muridan (2014) dan juga Roy Ellen (1986) menyebutkan hiruk pikuk perdagangan tersebut.
Para nelayanan di wilayah Seram Timur dan Tenggara menguasai jalur perdagangan sendiri, yang mereka sebut sebagai Sosolat. Jalur Sosolat biasanya melewati jalur Selatan yang memanjang dari pulau-pulau di Papua Barat, Seram Bagian Timur dan Tenggara, Timor, Bali, Banten, Bengkulu di Sumatera hingga Madras di India. Jalur ini merupakan jalur perdagangan ilegal di luar jalur perdagangan monopoli yang secara resmi dikuasai oleh kolonial Belanda.
Terdapat ratusan kapal dan perahu yang dikendalikan para pedagang dan pelaut Seram yang memuat berbagai bahan rempah-rempah untuk dijual ke Bali, Sumatera hingga India. Aktifitas tersebut sempat membuat harga komoditas rempah-rempah yang dimonopoli Belanda jatuh di pasaran dunia. Akibatnya, pemerintah Belanda marah besar. Dampaknya, Belnada menyebut orang-orang Seram Timur sebagai bajak laut dan penipu.
Menghadapi kenyataan ini, Gubernur Amboina Bernardus Van Pleuren (1785-1788 ) Gubernur Jendral Belanda di Batavia. Dalam suratnya Bernardus Van Plueren menyebut orang-orang Seram Timur yang menguasai aktifitas perdagangan tersebut sebagai “penipu yang paling tidak bisa dipercaya di seluruh dunia”. Akhirnya pemerintah Kolonial yang merasa dirugikan oleh aktifitas perdagangan tersebut melakukan “aksi penertiban” (hongi) secara besar-besaran melalui perang dan kekerasan.
Kapal-kapal dan perahu yang mendukung aktifitas perdagangan di tangkap, dibakar dan dimusnahkan. Para pelaut dan pembuat kapal berbadan besar juga ditangkap dan dibunuh. Bahkan sejumlah perkampungan di pesisir seram dibumihanguskan. Operasi penertiban tersebut menandai fase-fase paling awal dari runtuhnya budaya kemaritiman Maluku. Sebab sejak saat itu masyarakat semakin berjarak dengan lautnya.
Laut dipunggungi masyarakat Maluku. Halaman depan rumah yang tadinya mengahadap ke laut dipaska untuk berhadapan dengan gunung. Dapur rumah yang semula menghadap ke gunung, dipaksa untuk dibalik menghadap ke laut. Masyarakat dipaksa melalui berbagai cara untuk fokus hanya menanam dan merawat Pala dan Cengkeh yang dimonopoli kolonial Belanda.
Fase kedua yang turut menghancurkan budaya kemaritiman Maluku adalah saat Indonesia Merdeka. Ketika rezim Orde Lama serta Orde Baru memilih menfokuskan pembangunan pada wilayah daratan. Pembangunan juga hanya difokuskan di Jawa dan Sumatera sebagai daratan paling potensial bagi aktifitas pertanian dan perkebunan. Sering terdengar ucapan lawas, “Maluku adalah masa lalu, Jawa adalah masa kini dan Sumatera adalah masa depan”.
Pembangunan yang beroriantasi daratan memiliki implikasi serius. Sebab wilayah kepulauan seperti Maluku semakin merana, ditinggal dan dilupakan. Tidak ada kegiatan pembangunan yang strategis di Maluku. Laut dan kepulauan dianggap sebagai sesuatu yang tidak prospektif dan menghambat kemajuan. Aksi-aksi penjarahan terhadap hasil laut di Maluku oleh berbagai kapal nelayan asing juga dibiarkan tanpa ada hukuman yang maksimal.
Maluku yang tertinggal semakin sulit saja untuk berkembang. Apalagi tidak memperoleh sumber daya yang cukup untuk membangun wilayahnya. Padahal secara geografis Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil dan lautan yang luasnya mencapai 92%. Kekayaan Maluku strategis ini tidak dianggap penting oleh pemerintah pusat. Akibatnya, Maluku tetap berada pada posisi sebagau saalah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Adapun fase ketiga yang bisa dicatat sebagai bentuk keruntuhan peradaban kemaritiman di Maluku adalah ketika rezim reformasi di era SBY menolak inisiatif rakyat Maluku membentuk otonomi propinsi kepulauan. Suatu inisiatif yang dipercaya akan mampu mendorong percepatan pembangunan di Maluku. Secara teoritis akan terjadi mobilisasi sumber daya ekonomi dan politik untuk menopang pembangunan.
Meskipun secara retoris pemerintahan SBY selalu mengkampanyekan perubahan paradigma pembangunan yang semakin fokus pada aspek-aspek kelautan. Namun penolakan rezim SBY itu masih memperjelas bahwa kampanye kembali ke laut hanya lips service dan politik pencitraan semata. Pemerintah pusat memang telah membentuk kementerian kelautan dan perikanan, tetapi secara keseluruhan belum menunjukkan sebuah perubahan paradigmatik pembangunan yang fundamental yang mencakup seluruh aspek pembangunan nasional. (bersambung)
Penulis adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ambon.