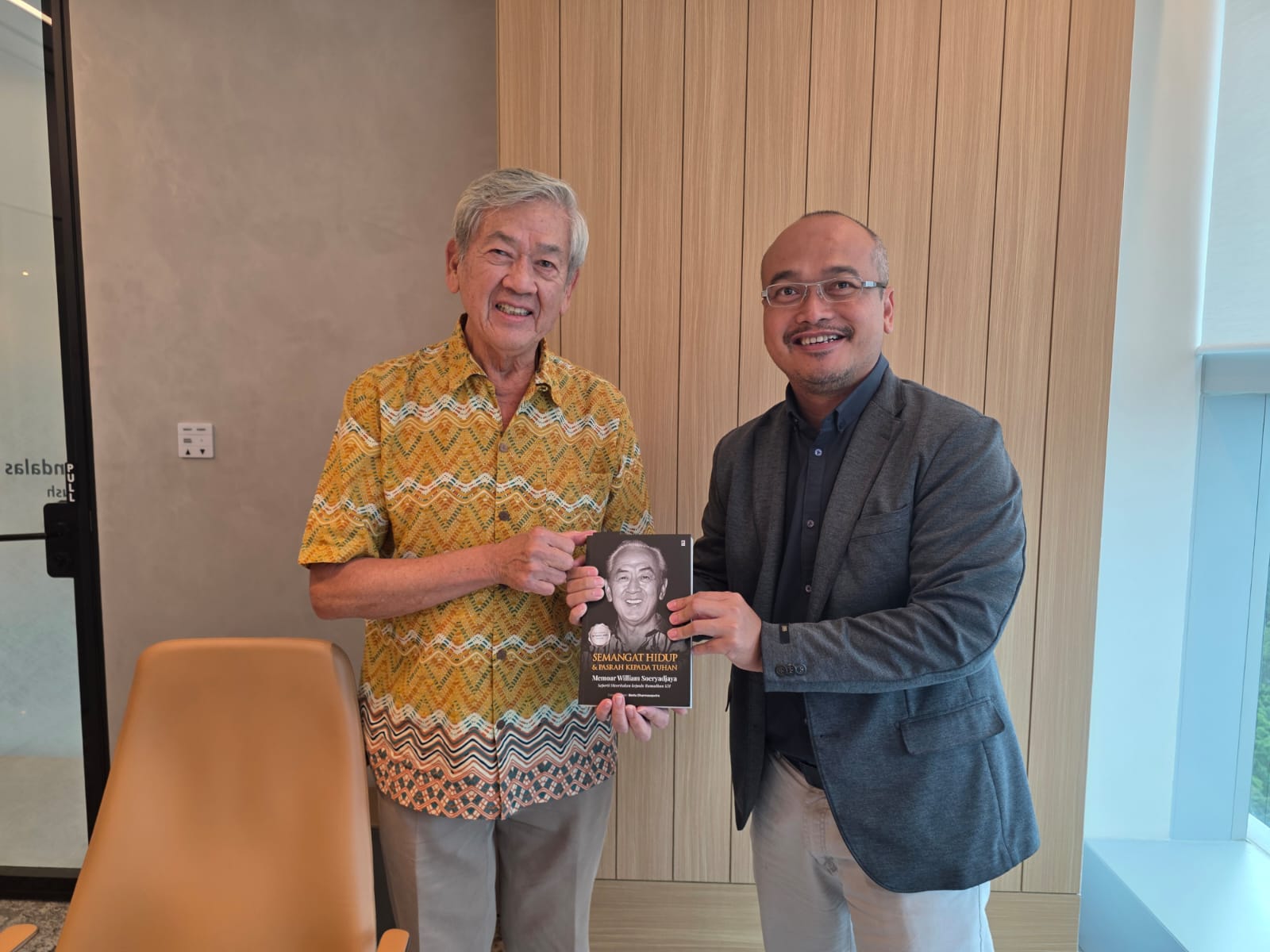Menanti Muhammadiyah Bersuara soal Privatisasi Air di Jakarta
Oleh: Noor Fajar Asa | Kader Muhammadiyah
DALAM Sidang Paripurna 8 September 2025, mayoritas fraksi DPRD DKI Jakarta menyetujui perubahan status PAM Jaya menjadi Perseroda. Keputusan itu membuka ruang lebih besar bagi logika bisnis dalam pengelolaan air, meski sejak awal air ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di tengah posisi strategis Muhammadiyah dalam isu-isu pelayanan publik dan advokasi sosial, organisasinya belum terlihat hadir di ruang perdebatan ini.
Hak atas air telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Instrumen itu menempatkan negara sebagai penjamin akses air minum yang aman, terjangkau, non-diskriminatif, serta bebas dari gangguan. Hak tersebut juga mencakup partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan air. Pendekatan itu tidak mengenal ruang bagi komodifikasi yang menempatkan air sebagai barang privat. Karena itu, ketika negara mengalihkan sebagian penguasaan air kepada pihak swasta, timbul pertanyaan tentang kesetiaan pada prinsip hak asasi dan mandat konstitusi.
Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini selaras dengan gagasan bahwa air adalah barang publik. Privatisasi menempatkan air dalam relasi pasar dan harga, bukan kebutuhan dasar yang harus dijamin.
Jakarta memiliki sejarah panjang privatisasi air. Pada 1997, PAM Jaya menandatangani dua kontrak konsesi: Palyja untuk wilayah barat dan Thames PAM Jaya—yang kemudian menjadi Aetra—untuk wilayah timur. Setelah itu, keluarga miskin kota mengalami hambatan besar dalam mengakses air karena tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai syarat sambungan. Mereka akhirnya membeli air dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada tarif resmi. Kebijakan yang semula diklaim akan meningkatkan efisiensi berubah menjadi praktik eksklusi sistemik.
Dampak privatisasi itu dapat dirasakan bahkan pada lingkungan yang dekat dengan jejaring Muhammadiyah. Warga yang menuju Kampus UHAMKA Pasar Rebo dari arah Kramat Jati akan melewati Gudang Air Pasar Rebo—penampungan air yang mulai beroperasi pada 1922. Bangunan bersejarah itu kini berada dalam pengelolaan Aetra. Lokasi tersebut menjadi pengingat bahwa infrastruktur air di Jakarta dibangun dengan orientasi pelayanan publik sejak era Batavia, sebelum berubah bentuk dalam skema kemitraan yang membuat banyak warga kesulitan mendapatkan air dengan harga wajar.
Persetujuan DPRD DKI atas perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda, langsung mengarah pada kebijakan. Perseroda membuka kemungkinan ekspansi skema bisnis, dan bagi sebagian kalangan, keputusan itu menunjukkan abainya wakil rakyat terhadap penolakan publik yang telah disuarakan sejak lama. Pada momen ini, absennya suara ormas-ormas Islam—termasuk Muhammadiyah—menjadi tanda tanya.
Muhammadiyah memiliki tradisi kuat dalam isu sosial kemasyarakatan. Organisasi ini mengelola sekolah, rumah sakit, dan kampus yang hadir untuk publik tanpa menempatkan pelayanan dasar sebagai komoditas. Karena itu, sikapnya terhadap privatisasi air memiliki bobot moral dan politik yang besar. Diamnya organisasi sebesar Muhammadiyah membuat ruang diskusi publik kehilangan salah satu penopang penting.
Privatisasi air bukan isu teknis. Ia bersentuhan dengan hak hidup warga, terutama mereka yang paling rentan. Ketika air semakin tunduk pada logika pasar, risiko eksklusi kembali mengemuka. Jakarta telah mengalami itu sejak 1997, dan sejarah tersebut seharusnya menjadi rambu peringatan.
Debat tentang air hari ini adalah debat tentang peran negara dalam memenuhi hak warganya. Muhammadiyah, dengan jejaring dan basis moralnya, memiliki posisi untuk turut mengarahkan diskusi. Publik menunggu apakah organisasi ini akan kembali hadir sebagai penyambung suara kelompok yang terdampak dan sebagai penegas bahwa air adalah hak, bukan komoditas. (*)