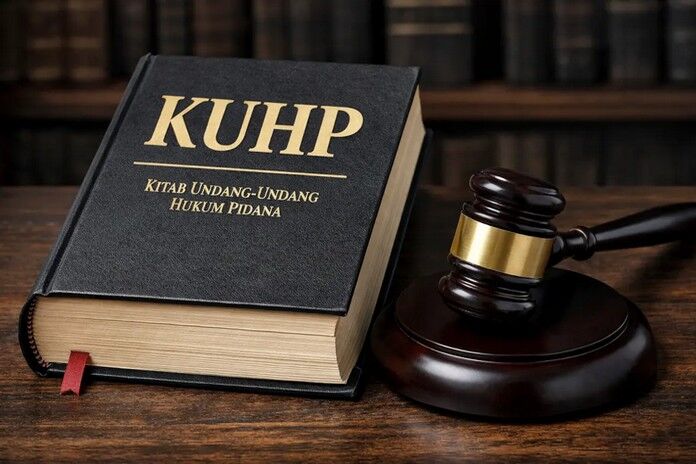Korupsi di Era Kini: Demokrasi yang Disandera Oligarki
Reformasi menjanjikan keterbukaan dan akuntabilitas, tapi dua dekade setelahnya, korupsi justru menjelma lebih cair dan sistemik. Dari pusat hingga daerah, dari parlemen hingga BUMN, praktik rasuah kini menjalar dalam tubuh demokrasi. Ketika uang menjadi bahasa kekuasaan, moral bangsa perlahan digadaikan.
Oleh: Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN
KETIKA Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sempat berujar bahwa korupsi di era sekarang “lebih meluas dan masif dibandingkan masa Orde Baru”. Sejatinya, lewat pernyataan itu, Mahfud sedang menyingkap paradoks besar demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 yang menjanjikan keterbukaan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, justru melahirkan bentuk baru korupsi yang lebih kompleks: bukan lagi sentralistik, melainkan terdistribusi dalam jaringan kekuasaan yang cair—menyebar dari pusat hingga daerah, dari legislatif hingga lembaga korporasi pelat merah.
Pada masa Orde Baru, seperti dicatat Robert Cribb dalam The Indonesian Killings (2001) dan Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (1988), korupsi terkonsentrasi di lingkar kekuasaan militer-birokrasi yang terkoordinasi. Korupsi adalah “kebijakan negara yang tak tertulis,” diatur dan dikontrol oleh elite pusat untuk menjaga stabilitas politik. Namun, setelah reformasi, ketika sistem politik menjadi lebih demokratis dan desentralisasi diberlakukan melalui UU No. 22/1999, peluang korupsi justru berlipat.
Sebagaimana diungkapkan Edward Aspinall dan Greg Fealy dalam Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation (2003), desentralisasi memperbanyak “titik bocor” baru. Korupsi tak lagi milik pejabat pusat, tapi juga kepala daerah, anggota DPRD, dan elite lokal yang kini memegang kendali anggaran. Akibatnya, seperti dikatakan Mahfud, korupsi “bisa dilakukan bahkan sebelum anggaran disahkan.”
Klasemen Liga Korupsi Indonesia: Sebuah Potret Ironi
Hingga 2025, Indonesia seakan memiliki “liga” sendiri—Klasemen Liga Korupsi Indonesia. Di puncaknya, kasus Pertamina dengan dugaan kerugian Rp968,5 triliun, disusul PT Timah Rp300 triliun, dan BLBI Rp138 triliun. Jika dijumlahkan, seluruh kasus besar ini menembus Rp1.588 triliun—angka yang nyaris tak terbayangkan.
Menurut Transparency International (Corruption Perception Index 2024), skor Indonesia turun menjadi 34/100, peringkat 115 dunia, menandakan memburuknya persepsi publik terhadap integritas birokrasi. Angka ini selaras dengan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat lebih dari 700 kasus korupsi sepanjang 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp120 triliun.
Namun kini, korupsi bukan lagi sekadar pencurian uang negara, melainkan sistem yang menopang patronase politik. Seperti dijelaskan Vedi R. Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia (2010), oligarki ekonomi dan politik yang dulu bersembunyi di balik kekuasaan Soeharto kini bertransformasi melalui partai politik dan bisnis negara. Mereka menggunakan mekanisme demokrasi—pemilu, tender, APBN—sebagai instrumen untuk menyalurkan rente kekuasaan.
Demokrasi Tanpa Etika: Korupsi sebagai Kultur
Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) pernah mengingatkan bahwa korupsi sering tumbuh subur dalam masa transisi politik. Ketika lembaga demokrasi belum mapan, tetapi akses kekuasaan terbuka, korupsi menjadi pelumas sistem. Inilah yang terjadi di Indonesia.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris (2015) menyebut fenomena ini sebagai “korupsi elektoral”: praktik uang politik, jual-beli proyek, dan politik balas jasa yang dilembagakan. Partai membutuhkan biaya besar untuk memenangkan pemilu, pejabat membayar “mahar politik” untuk mencalonkan diri, dan kompensasinya dibayar melalui proyek negara. Maka, korupsi bukan lagi penyimpangan, tetapi bagian dari “rantai ekosistem kekuasaan.”
Jika dikonversi, Rp1.588 triliun cukup untuk membiayai seluruh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi bagi 52 juta anak Indonesia selama satu dekade, seperti dihitung dalam World Bank Education Report (2022). Atau, bisa memberi layanan kesehatan BPJS gratis bagi seluruh warga selama 11 tahun. Namun uang itu lenyap dalam pusaran kerakusan.
Sebagaimana dikatakan Mahfud MD, “Dulu uangnya tersedia baru dikorupsi. Sekarang, uangnya belum ada, sudah dikorupsi.” Pernyataan ini menggambarkan transformasi moral bangsa yang kian tergerus: dari korupsi yang bersifat administratif menjadi korupsi yang bersifat imajiner—mencuri bahkan dari anggaran yang belum lahir.
Menuju Etika Publik Baru
Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan regulasi. Seperti dikemukakan oleh Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption (1988), korupsi adalah hasil dari “monopoli kekuasaan + diskresi tanpa akuntabilitas – transparansi.” Karena itu, solusinya harus struktural dan kultural sekaligus.
Pertama, sistem politik perlu direformasi agar pembiayaan partai lebih transparan. Kedua, penguatan *whistleblower protection* harus diprioritaskan agar pelapor kasus korupsi tidak dibungkam. Ketiga, reformasi birokrasi digital perlu dijalankan secara menyeluruh untuk meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan pengusaha.
Namun lebih dari itu, bangsa ini membutuhkan moral recovery—pemulihan etika publik yang berpijak pada kesadaran bahwa setiap rupiah dari pajak rakyat adalah darah kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, gagasan Corruption as a Human Rights Violation (UNCAC, 2019) menjadi relevan: korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial rakyat miskin yang dirampas masa depannya.
Indonesia hari ini bukanlah negara miskin, tetapi negara yang “dimiskinkan.” Demokrasi yang semestinya menjadi pagar moral kini berubah menjadi panggung transaksi. Bila uang rakyat terus dijadikan bahan bakar kekuasaan, bukan pembangunan, maka pernyataan Mahfud MD hanyalah epitaf: bahwa reformasi telah gagal menyehatkan moral bangsa.
Korupsi bukan lagi soal siapa yang mencuri, tetapi soal siapa yang diam. Dan selama diam dianggap aman, maka 1,6 kuadriliun rupiah berikutnya hanyalah soal waktu. (*)