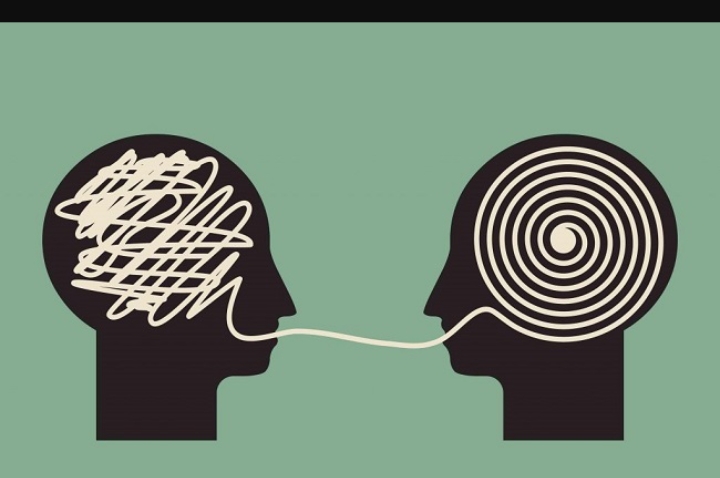EDITORIAL
Senin, 7 Desember 2020 sampai Selasa, 7 Desember 2021: Di Mana Aktor Pembunuh Enam Laskar FPI Bersembunyi
SETAHUN yang lalu peristiwa tragis itu terjadi. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, mereka harus dibunuh dengan peluru tajam yang menghujam ke badan. Tidak hanya bekas tembusan peluru, beberapa bagian tubuhnya pun terkelupas dan melepuh, diduga karena diseret atau diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh para pembantai yang dilakukan oleh anggota polisi. Hari ini, 7 Desember 2021, peristiwa tersebut genap setahun. Ya, setahun sudah, peristiwa pembantaian terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) berlalu. Trageti itu terjadi pada 7 Desember 2020. Enam orang laskar yang pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) dan keluarga menuju pengajian keluarga inti di wilayah Karawang, Jawa Barat, harus mengerang nyawa. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Rombongan HRS dan keluarga sudah mulai dibuntuti sejak berangkat dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat berada di jalan tol, terjadi aksi saling memotong jalan, antara mobil yang ditumpangi laskar dengan mobil yang awalnya tidak diketahui dikemudikan siapa. Sebab, tidak ada pakaian resmi yang digunakan oleh pengemudi dan penumpang yang memepet mobil laskar. Juga tidak ada peringatan atau kode yang menyebutkan mereka petugas polisi. Akan tetapi, yang pasti, laskar yang terdiri dari dua mobil (total 10 orang laskar) berusaha mengamankan HRS dan keluarga. Di dalam mobil HRS, ada istri, anak, menantu dan cucu-cucunya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, perjuangan laskar mengamankan dan menyelamatkan HRS dan keluarga berhasil. Penguntit tidak bisa mendeteksi atau mengikuti mobil yang ditumpangi Imam Besar FPI itu. HRS dan keluarga selamat. Akan tetapi, tidak demikian dengan enam orang laskar yang akhirnya gugur dalam membela dan melindungi sang guru, sang imam yang sangat mereka cintai dan kagumi itu. Ya, tugas mereka mengawal HRS dan keluarga, apa pun risikonya. Menjelang shalat Subuh, Munarman waktu itu Seretaris Umum FPI, mengirimkan pesan berantai. Isinya, “Enam orang pengawal Habib Rizieq Syihab hilang diculik orang tidak dikenal (OTK).” Wajar dia sebut diculik OTK, karena saat peristiwa terjadi, tidak ada orang yang menduga yang melakukan penculikan dan pembantaian itu adalah anggota Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Wajar disebut diculik, karena berdasarkan pantauan pembicaraan komunikasi yang dimiliki FPI, para laskar sempat melaporkan jika mereka diserang orang tidak dikenal. Peristiwa menjadi terang-benderang. Siang hari, Senin, 7 Desember 2020, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inpektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengumumkan anggotanya yang menembak enam laskar itu. Saat jumpa pers, ia antara lain didampingi Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman (Panglima Komando Daerah Jaya waktu itu), kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Fadil mengaku, anak buahnya “terpaksa” menembak laskar, karena melakukan perlawanan. Nah, mari kita telusuri berbagai hal yang menyangkut tewasnya Muhammad Reza, Lutfi Hakim, M.Suci Khadafi, Ahmad Sofiyan, Faiz Ahmad Syukur dan Andi Oktaviana. Jika kita ikuti penuturan Fadil yang menyebutkan melakukan perlawanan, itu sangat mustahil dan tidak masuk akal. Hal itu bisa dilihat dari rekonstruksi yang dilakukan aparat kepolisian di KM-50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Saat rekonstruksi, terlihat enam laskar masih hidup. Dua di antaranya terlihat disuruh jalan merangkak. Tidak terlihat ada benda yang membahayakan di dalam tubuh mereka (polisi mengatakan ditemukan senjata rakitan dan samurai di mobil). Artinya, semua barang berbahaya sudah di tangah polisi. Keenam laskar kemudian disuruh masuk ke mobil lain yang sudah disiapkan polisi. Artinya, jelas pembunuhan terhadap enam laskar itu tidak dilakukan di KM-50. Akan tetapi, dilakukan di dalam mobil atau di suatu tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Wallohu a’lam. Meski tidak ditembak atau dibunuh di tempat tersebut, akan tetapi peristiwa itu lebih dikenal dengan Tragedi KM-50. Banyak hal yang dirasakan kurang sinkron, antara keterangan pihak kepolisian dengan saksi di tempat, maupun keterangan dari pihak FPI. Keterangan polisi berubah-ubah dan tidak sesuai dengan rekonstruksi (rekonstruksi lebih mendekati fakta keterangan dari FPI). Keterangan FPI yang disampaikan Munarman, selalu konsisten dan hampir sama dengan keterangan yang mulai terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat dua orang anggota polisi duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Banyak kejanggalan. Banyak cerita yang seakan-akan dikarang-karang. Akan tetapi, begitu di hadapan hakim PN Jaksel, semua tidak bisa lagi mengarang cerita. Sebab, mereka yang menjadi saksi dan terdakwa disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, disumpah dengan Kitab Suci AlQur’an di atas kepala. Sumpah seperti itu, bagi seorang yang beragama Islam (walaupun hanya Islam KTP), sangat berat. Hingga sekarang persidangan perdana yang dimulai 18 Oktober 2021 itu masih berlanjut. Dua orang polisi menjadi terdakwa, yaitu Ispektur Polisi Dua (Ipda) M Yusmin Ohorella, dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan. Awalnya ada tiga orang anggota polisi menjadi terdakwa. Akan tetapi, satu orang atas nama Elwira Priyadi Zendrato, kasusnya ditutup karena yang bersangkutan mati dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Peristiwa kecelakaan yang menyebabkan ia mati terjadi tanggal 3 Januari 2021, tetapi baru diumumkan Jumat, 26 Maret 2021. Wah hebat sekali polisi kita, karena hampir tiga bulan baru diumumkan? Nah, hingga sekarang dua orang anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus pembantaian enam laskar FPI sama sekali tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan. Padahal, ancaman pidana terhadap terdakwa 15 tahun penjara. Sedangkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP menjelaskan, penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Sangat tidak adil! Diskriminatif ! Sangat melukai hati rakyat! Padahal, tidak sedikit juga polisi yang dihukum atasan karena sebuah kesalahan. Misalnya, anggota polisi Brigadir NP yang membanting (smackdown) mahasiswa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dihukum 21 hari penjara, turun pangkat dan tidak punya jabatan. Bisa juga peristiwa teranyar, yaitu anggota polisi RB yang dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. RB ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. RB dijerat pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Lalu, mengapa terhadap dua orang pembunuh enam laskar tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan? Padahal, cara menembaknya sangat sadis. Diduga ditembak dari jarak dekat, dan lobang peluru ada yang sampai 2 dan tiga dalam pada jenazah laskar. Pembunuhan yang sadis dan kejam, karena terdapat luka yang mengerikan, mirip dibakar atau diseret di aspal? Apakah karena mereka pelaku saja yang mendapatkan perlindungan dari atasan atau dari pihak tertentu? Mengapa tidak ada anggota polisi lain yang menjadi tersangka? Padahal, di pengadilan, sudah mulai terkuat siapa yang mengeluarkan surat perintah. Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat disebut menjadi orang yang memerintahkan tujuh anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap rombongan Muhammad Rizieq Syhab, dengan surat perintah penyelidikan (sprindik). Hal itu dikatakan, Toni Suhendar dalam kesaksiannya yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menewaskan 6 anggota laskar FPI, di PN Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2021. Toni sendiri merupakan anggota Sub Direktorat Resimen Mobil Direktorat Reserse Kriminam Umum (Subdit Resmob Ditreskrimum) Polda Metro Jaya yang juga mendapat mandat ikut melakukan pembuntutan tersebut. Dari keterangan Toni Suhendar itu, juga semakin tekuak, yang diperintahkan membuntuti ada tujuh anggota polisi. Jika yang sudah ditetapkan menjadi tersangka 3 orang (satu kasus ditutup karena mati), lalu ke mana empat anggota polisi lain yang membuntuti itu? Apakah tugas mereka hanya membuntuti, mengamati, atau turut mengeksekusi? Kemana sopir mobil yang digunakan mengangkut enam laskar? Akan tetapi, karena target utama mereka bukan laskar, melainkan Habib Rizieq Syihab, maka semua masih serba misteri. Semua yang mereka lakukan, apakah membuntuti, mengintai, membunuh, tidak lama lagi akan terungkap semua. Termasuk aktornya siapa? Jika tidak terungkap di pengadilan dunia, yang pasti di pengadilan akhirat akan terbuka secara terang-benderang. **
Jokowi Sangat Takut Angka 212
WUIH, 212 kini menjadi angka kramat, tetapi bukan dikramatkan. Jokowi sangat takut dengan angka itu. Terdiri dari tiga angka, ia muncul dari peristiwa 2 Desember 2016. Angka tersebut muncul setelah aksi besar-besaran dilakukan oleh umat Islam, yang menuntut agar Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang kala itu Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta dipenjara karena menista agama AlQuran dan agama Islam. Ahok akhirnya divonis dua tahun dan langsung dipenjara karena penistaan terhadap agama Islam. Ia pun mengakui kesalahanan melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51, karena sama sekali tidak mengajukan banding. Angka 212 sangat populer di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan, tidak sedikit penganut agama lain mengagumi angka tersebut. Sebab, angka itu membuat inspirasi kepada semua pihak, betapa umat Islam sangat damai, sangat menghormati penganut agama lain. Umat Islam sangat toleran. Buktinya, peserta aksi juga diikuti penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kaum wanitanya datang tanpa jilbab dan aksesoris Islam. Tetapi, mereka aman-aman saja. Tidak ada gangguan. Tidak hanya sampai itu, umat Islam juga pencinta lingkungan dan kebersihan. Angka 212 semakin populer, setelah para tokoh agama Islam (kiai, habaib, ustaz) mampu mengajak jemaahnya melakukan aksi super damai. Oleh karena itu, aksi tersebut (sejak 2016) dan diperingati hampir tiap tahun – kecuali 2020 karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) turut mewabah di Indonesia, disambut antusias. Bahkan, pada aksi 2018, banyak peserta baru (tidak ikut tahun 2016). Mereka ikut-ikutan, karena ingin mendulang suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Banyak caleg yang datang. Banyak pelajar dan mahasiswa datang, hanya sekedar rekreasi. Jutaan umat turun ke jalan. Seputar Monas pada 2-12-2016 penuh dengan lautan manusia. Bahkan, para pendemo mengular ke bebapa ruas jalan lainnya. Tidak ada angka resmi yang bisa menghitung jumlahnya. Ada yang memperkirakan 1,5 juta orang, tiga juta orang dan bahkan tujuh juta orang. Peristiwa 212 tahun 2016 bertepatan dengan hari Jum’at. Umat Islam pun shalat Jum’at di sekitar Monas dan sekitarnya. Hujan deras yang turun menjelang pelaksanaan shalat Jumat, sama sekali tidak mengurangi minat dan kekhusukan umat dalam melaksanakan ibadah wajib (bagi laki-laki) tersebut Khutbah Jum’at yang disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab (HRS) merupakan pemompa semangat juang jemaah. Bahkan, tidak sedikit yang meneteskan air mata, saat alunan ayat suci Alqur’an yang dibawakan sang imam. Jumlah tidak seberapa penting. Akan tetapi, yang paling penting adalah getaran dari aksi damai tersebut yang memaksa Presiden Joko Widodo harus hadir di tengah umat. Kenapa memaksa? Karena dalam aksi sebelumnya 4-11-2016, Jokowi memilih kabur ke Bandar Udara Sukarno-Hatta. Aksi yang dikenal dengan 411 itu juga ternoda oleh ulah provokator, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi. 212 tahun 2016 adalah awal sejarah baru perjuangan umat. Aksi super damai itu, benar-benar damai. Begitu selesai acara, sampah di sekitar Monas pun bersih disapu dan dikumpulkan oleh jamaah sendiri yang membawa kantong plastik dari rumah masing-masing. Ranting pohon pun tidak ada yang patah. Jangankan ranting pohon, rumput yang tumbuh di sekitar Monas pun tidak ada yang rusak akibat diinjak. Harap maklum. Begitu ada orang yang mau menginjak rumput, jemaah pun menegur dan memperingatkannya. Jika membandel, jemaah yang melihatnya pun menyorakinya, dan bahkan ada yang menarik tangan, supaya orang tersebut tidak menginjak rumput hijau yang indah dipandang mata itu. Aksi damai, super damai! Itu bukan isapan jempol. Reuni Akbar 212 yang digelar tahun 2017 pun juga super damai. Padahal, jumlahnya jauh lebih banyak. Diperkirakan mencapai 13 juta orang. Walau dari pihak kepolisian memperekirakan hanya lima juta orang. Upaya menggembosi acara pun terus dilakukan aparat kepolisian. Di setiap wilayah, ada penyekatan. Bahkan, ada ancaman terhadap pemilik armada bus yang mengangkut peserta aksi. Jika membandel, trayeknya akan dicabut. Oleh karena itu, tidak sedikit juga calon peserta yang “dipaksa” putar balik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang melakukan perlawanan. Tuduhan negatif pun dialamatkan kepada peserta. Mereka dibayar dan sebagainya. Siapa yang mampu membayar umat sebanyak itu? Apalagi, sebagian juga datang dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan, peserta dari Sumatera Barat mencarter burung besi itu, hanya karena ingin mengenang peristiwa tersebut. Siapa peserta yang mau dibayar? Mereka merogoh isi kantong sendiri. Kaum ibu atau emak-emak, misalnya, mengumpulkan uang buat donasi (baik disumbangkan dalam bentuk uang tunai) maupun membeli makanan dan minuman yang siap dibagikan kepada peserta aksi. Karena melimpahnya makanan dan minuman, maka jangan heran banyak yang “kekenyangan”. Siapa yang membayar itu semua? Dan siapa yang mau dibayar? Yang turun, mulai dari Direktur Utama Perusahaan, Direktur Rumah Sakit, manajer perusahaan dan karyawan. Pedagang pun meninggalkan usahanya karena ingin ikut aksi. Tidak sedikit pengusaha ikut aksi demo. Mau tahu buktinya? Itu loh, jas hujan yang dipakaikan secara simbolis kepada peserta aksi dari Ciamis yang datang berjalan kaki dan kehujanan. Emang jumlah jas hujan itu Cuma 100 pasang? Oh, tidak! Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 50 juta. Itu sumbangan dari seorang pengusaha China mualaf. Berbagai usaha menggembosi aksi 212 terus dilakukan. Aksi reuni 212 tahun 2021 ini tidak ketinggalan. Izin yang diajukan panitia untuk melaksanakan aksi di Monas, ditolak dengan alasan belum dibuka karena masih Covid-2021. Masuk akal. Izin mengadakan kegiatan di Patung Kuda, ditolak polisi. Alasannya, sama masih suasana pandemi. Padahal, sudah berapa banyak yang melakukan aksi di tempat tersebut? Belum lama, buruh melakukan aksi juga. Panitia tidak kehabisan akal. Mereka merencanakannya di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, menjelang hari H, datang surat dari pengurus masjid, yang menolak kegiatan aksi dilakukan di tempat tersebut. Dugaan kuat, aparat keamanan menekan pihak keluarga supaya mengeluarkan surat penolakan. Andaikan, Arifin Ilham masih hidup, dia pasti menerimanya, karena ia aktif dalam kegiatan 212. Tidak hanya mengerahkan jemaahnya, tetapi juga memberikan dukungan materil, berupa makanan dan minuman. Walau sudah ditekan habis-habisan, panitia acara terus berupaya melaksanakan kegiatan. Sekuat tenaga mereka lakukan. Akhirnya upaya mereka gagal. Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pun ditutup secara total mulai semalam pukul 24.00 sampai Kamis, 2 Desember 2021, pukul 21.00. Tetapi, penutupan tersebut tidak akan menyurutkan umat yang ingin melakukan aksi. Tidak hanya menutup, 4.218 personil gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga guna mencegah aksi Reuni 212 di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ancaman pun dikeluarkan polisi. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Marsudianto mengatakan, pengamanan tersebut merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19. Kegiatan Reuni 212 bukan bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, layaknya aksi unjuk rasa. “Ini adalah kegiatan keramaian,” ujar Marsudianto. Ia pun mengeluarkan jurus ancaman. Kegiatan Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yakni mengadakan pesta umum dan keramaian umum. (1) Bila pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Akan tetapi, umat tidak setakut Jokowi terhadap angka 212. Umat tidak gentar dengan ancaman yang dikeluarkan Marsudianto itu. Umat, hari ini tetap keluar dan melakukan aksi masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, apakah polisi mau menangkap seluruh umat yang turun ke jalan? Ayo, silahkan biar penjara penuh lagi selama dua pekan? Atau denda? Ya tidak apa-apa. Uang dikumpulkan saja. Lumayan buat mencicil utang Jokowi. Rakyat sudah bosan menunggu uang Rp 11.000 triliun di kantongnya yang sampai sekarang masih ghaib. Apalagi harga racun kalajengking, yang kata Jokowi, mahal. Tetapi, tidak ada ajakan cara beternaknya. Ghaib lagi!
Menghitung Hari Rezim Jokowi
KRISDAYANTI. Dari penyanyi menjadi politisi. Sang diva sempat membetot perhatian publik karena blak-blakan menghitung penghasilan sebagai anggota DPR. Jelas membuat kaget publik. Terlampau besar dibandingkan hasil legislasi para wakil rakyat di Senayan. Semasa di puncak karier seni, salah satu lagu Krisdayanti yang booming, juga masih urusan menghitung. Kali ini bukan soal income. Tapi menghitung hari. Memberi deadline agar kekasihnya berperilaku jujur. Ketulusan hati. Jika tidak bisa, matikan saja kobaran cinta, alias bubar jalan. Ketulusan, kejujuran inilah yang juga didamba seluruh penduduk negeri ini. Kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan semakin buruk, dan jauh dari konsep negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Tahun lalu, tepatnya 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pun, sudah mengingatkan atas tata kelola penyelenggaraan negara, khususnya di masa pandemi Covid-19. Namun suara keprihatinan yang tertuang dalam Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu, tidak mendapatkan respons pemerintah. Padahal timbunan persoalan semakin besar dan memberatkan rakyat. Utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI semakin tidak terkendali, dan berpotensi gagal bayar menurut Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, utang pemerintah sudah tidak terkendali sebelum pandemi Covid-19, demi membangun proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan merupakan prioritas kebutuhan rakyat. Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah justru tidak dapat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam, tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menimbulkan deforestasi dan kerusakan sumber daya alam yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup generasi mendatang. Ironisnya, rezim jokowi terus memburu pajak yang menambah berat kehidupan masyarakat lapisan bawah. Dari pajak sembako, pendidikan hingga kesehatan. Aspek lain yang disoroti KAMI adalah peran para pejabat di masa pandemi. Mereka penentu kebijakan penanganan pandemi sekaligus menjadi pelaku bisnis vaksin Covid-19 dan PCR. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan. Karena itulah dalam Maklumat kedua pada 12 november 2021 yang diteken Presidium KAMI Jenderal TNI Purnawirawan GATOT NURMANTYO, ROCHMAT WAHAB dan DIN SYAMSUDDIN, ada 3 persoalan besar yang mendesak diperbaiki pemerintah. Pertama. Cengkeraman Oligarki dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi. Bersatunya elit ekonomi dan politik menyebabkan roda ekonomi nasional dijalankan secara serampangan dan brutal. Sudah seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai nilai sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi. Kedua. Presiden gagal dalam mengelola roda pemerintahan. Kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktek rente kebijakan dan korupsi semakin memburuk tidak terkendali. Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral. Keserakahan di tengah derita pandemi. Selain tidak fokus memikirkan nasib rakyat, kepemimpinan nasional tidak punya kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan. Padahal hal ini diperlukan untuk langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia. Ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020, seharusnya menjadi momentum pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta mengusut potensi kerugian dari perilaku korupsi serta rente atas kebijakan penanganan pandemi. Dan sesuai putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun 2021, maka anggaran COVID yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus dengan persetujuan DPR. Kini saatnya pemerintah membuka ruang kepada publik untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Negeri ini perlu diselamatkan, dari ancaman kerusakan moral dan kehancuran di semua sektor kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, sama halnya menanti kehancuran. Tinggal menghitung hari.
Belut Tak Selicin Luhut
BELUT sering dijadikan perumpamaan bagi orang yang pandai menghindar, berkelit, dan berbohong. “Licin bagai belut,” begitu bunyinya. Padahal, belut sendiri tak pernah berbohong. Licinnya belut bukan karena berkelit atau lari dari tanggung jawab. Ia diciptakan Tuhan sebagai binatang yang tubuhnya penuh lendir sehingga sulit ditangkap tangan manusia. Tapi selicin-licinnya belut, ia masih mudah ditangkap. Ada belut yang hidup di sawah, ada juga yang diternakkan di rumah-rumah. Kini belut dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang masih tinggi. Belut banyak memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam setiap 100 gram belut, terdapat banyak sekali kandungan gizinya. Mulai dari kalori senilai 303 kkal, protein 18,4 gram, lemak 27 gram, kalsium 20 miligram, fosfor 200 miligram, zat besi 20 miligram, dan masih banyak lagi. Lalu apa hubungan belut dengan Luhut. Keduanya sama sama licin. Namun, belut licin secara alami, sedangkan Luhut licin dibuat-buat. Ia pintar berkilah. Ia juga pintar menggunakan – entah staf pribadi atau staf kementerian – untuk menjadi juru bicara. Ia pandai berargumen, berteori, dan menghindar bahkan menantang pengkritiknya untuk membuktikan tuduhan KKNnya. Saat nama Luhut disebut Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam sebuah diskusi daring, Luhut murka. Haris dan Fatia menyebut Luhut sebagai salah satu pejabat yang berada di balik bisnis tambang emas dan rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut lantas menggugat balik Haris sebesar Rp100 Miliar. Saat Luhut menjalankan peran ganda sebagai penguasa sekaligus pengusaha dalam pengadaan PCR, semua orang di sekeliling Luhut kompak memagarinya. Luhut menyelinap di balik kaum loyalis yang setia menjadi bempernya. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua menteri ini diduga terlibat dalam bisnis PCR. KPK diminta mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. Nyatanya sampai sekarang belum ada perkembangan atas laporan itu. Sepertinya KPK meniti jalan basah bertabur oli sehingga takut terpeleset untuk sekadar mandatangi kantor Luhut. Kalau perlu KPK langsung menggeledahnya untuk menjawab dugaan-dugaan yang bisa saja salah. Itulah Luhut, selalu ada jalan mulus di depannya. Luhut selalu sukses berkelit, berkilah dan beralibi. Ia lebih licin dari belut. Tak hanya KPK yang tak kuasa mengusut Luhut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun tak mampu menasihati Luhut agar lebih Pancasilais. Badan yang diberi wewenang penuh menuntun dan memandu setiap warga negara – termasuk Luhut untuk patuh dan tunduk pada doktrin BPIP, tak juga punya daya untuk sekadar memberi wejangan kepada Luhut. Akrobat Luhut di mata BPIP tampaknya tak begitu menarik. BPIP lebih terarik menyoal suara merdu santri-santri kecil innocent, polos, dan bersih. Padahal, apa yang dilakukan LBP jelas melanggar Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia tidak berperikemanusiaan karena di tengah wabah Covid-19, sebagai menteri masih sempat berbisnis obat dan alat Covid. Ia tidak beradab, di tengah penderitaan rakyat, marah-marah dan menampakkan arogansi saat kasusnya dilaporkan ke KPK. Ia seakan tak melihat kesulitan rakyat. Ia juga seakan tak mendengar jeritan rakyat. Dan hatinya seakan tak tersentuh mengetahui kehidupan rakyat makin sengsara selama dua tahun terakhir akibat pandemi dan korupsi. Anggaran pandemi yang seharusnya masih berjalan sampai hari ini, ternyata sudah lama berhenti. Sangat mungkin dikorupsi seperti yang dilakukan Juliari. Luhut seakan tak melihat betapa perjuangan rakyat bertahan hidup di tengah pandemi begitu sulit. Ia juga tak tampak menunjukkan simpati dan empati terhadap penderitaan rakyat. Tak ditemukan wajah sejuk di muka Luhut. Yang ada hanyalah marah, marah, dan marah. Apa sih yang tidak mungkin dilakukan Luhut. Semua bisa dilakukan. Semua beres di pundak mantan tentara itu. Tindakannya cepat, omongannya ceplas-ceplos. Mimiknya menakutkan. Maka ketika duit penanganan pandemi menggelontor begitu dahsyat, Luhut melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia ikut serta sebagaimana diakui sendiri oleh jubirnya Jodi Mahardi. Secara tersirat, pernyataan Jodi membenarkan Luhut terlibat dalam bisnis PCR. Datanya jelas, akta perseroan ada, dokumen tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga nyaris bahkan mustahil dibantah. Kenapa Luhut begitu mudah ikut bisnis PCR, karena Luhut yang ikut bisnis PCR itu bukan Luhut yang tukang kuli angkut. Bukan Luhut yang lain, tetapi Luhut yang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta puluhan jabatan strategis lainnya. Oleh karenanya jalannya mulus. Itulah yang namanya conflict of interest. Masih mau berkilah, Tuan Luhut?
Sukmawati Murtad, Solusi Terbaik Bagi Kelompok Islamphobia
AKHIRNYA dengan jujur Sukmawati menyampaikan niatnya untuk pindah agama dari Islam ke Hindu tepat di hari ulang tahunnya yang ke 70 di Soekarno Centre Bali. Arya Wedakharna tim sukses di balik prosesi ritual pindah agama ini juga membenarkan sesuai yang diberitakan banyak portal on line media massa. Tak tanggung-tanggung, Presiden RI Jokowi, Menteri Agama, serta keluarga besar Soekarno akan diundang dan acaranyapun juga akan dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat umum. Beragam komentar dapat kita lihat hasil celoteh para netizen baik itu pro dan kontra. Apapun itu alasannya, perpindahan agama Sukmawati dari Islam ke Hindu, yang dipublikasi secara sakral, terbuka dan besar-besaran kepada publik adalah hak preogratif Sukmawati. Namun yang menarik dari berita ini adalah tanggapan dari kelompok Islam itu sendiri. Justru menyambut positif hal ini. Malah ada yang mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebenarnya, prosesi perpindahan agama di bumi nusantara ini adalah hal yang biasa. Apakah itu dari kristen ke Islam (mualaf), atau dari Islam ke kristen (murtad), maupun dari agama lainnya seperti Hindu dan Budha. Namun khusus Sukmawati memang agak sedikit berbeda. Karena, prosesi ritual perpindahan agama ini entah sengaja atau tidak, beritanya seakan dibuat begitu heboh. Sampai mengundang kepala negara dan menteri agama segala. Namun menariknya juga adalah tanggapan dari kelompok ummat Islam itu sendiri. Yang kadang kocak, lucu, satire, tapi dominan tak masalah atau malah mendukung. Kata mendukung ini yang menarik kita bahas dalam tulisan ini. Karena tentu hal itu punya alasan tersendiri bagi ummat Islam. Dimana kalau kita mapping menjadi beberapa jenis alasan sebagai berikut : Pertama, rekam jejak Sukmawati yang acap dilaporkan oleh kelompok ummat Islam atas ungkapan Sukmawati itu sendiri yang banyak menyakiti hati ummat Islam. Khususnya dalam isu “tusuk konde” dan “kidung Vs suara azan”. Namun sayang, seperti biasa, laporan ummat Islam atas dugaan penistaan agama ini tidak diproses penegak hukum sampai saat ini. Kedua, performance keislaman Sukmawati selama ini juga tidak kelihatan di mata publik. Apakah itu cara beribadahnya, kontribusi sosialnya, termasuk pikiran dan ucapannya yang banyak melahirkan kontroversial di tengah masyarakat. Ketiga, dengan “murtad”nya Sukmawati keluar dari agama Islam, akan lebih baik dari pada beliau masih mengaku Islam tapi setiap ungkapan dan ucapannya sering menyakiti hati ummat Islam. Maka akan semakin jelas batas hitam-putihnya seorang Sukmawati di mata masyarakat. Dan semoga setelah ini, beliau tak lagi merecoki ibadah ummat Islam dan bisa fokus ibadah menurut agama baru yang dianutnya. Keempat, dengan keluarnya Sukmawati dari Islam, ibarat duri keluar dari dalam daging. Karena bagi sebagian kelompok Islam sendiri selama ini Sukmawati ibarat duri dalam daging. Ngaku Islam tapi menyakitkan hati ummat Islam. Buktinya beliau berulang kali dilaporkan ke Polisi walaupun tidak diproses Kelima, yang menarik adalah bagi kelompok Islamphobia. Yang menyambut hal ini dengan gegap gempita proses murtadin Sukmawati ini. Kelompok ini langsung menggoreng isu ini sedemikian rupa, dengan narasi toleransi dan kebhinekaan. Karena bagi kelompok Islamfobhia ini (meskipun mereka juga ngaku Islam), salah satu indikator penganut paham toleransi dan kebhinekaan itu adalah “semua agama itu sama”. Dan tidak mempermasalahkan perpindahan agama itu karena dianggap tidak terlalu penting. Berbeda dengan kelompok Islam Aswaja yang mayoritas di Indonesia. Yang tetap menganggap agama itu adalah masalah private, masalah akidah dan tauhid yang tak bisa ditawar dengan urusan dunia atau pikiran sekulerisme liberal. Keenam, berharap setelah Sukmawati hal ini juga dapat diikuti oleh Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kunthadi, Ade Armando, Guntur Romli, atau lainnya. Biar semakin jelas batas polarisasi mana yang mengaku kelompok Islam fundamentalis yang dicap kadrun, radikal dan intoleran. Dan mana kelompok Islam penganut paham sekuler, liberal, syiah, atau Islam Nusantara istilah mereka. Kenapa ini perlu diperjelas? Agar masyarakat segera tahu dan tidak bingung lagi. Karena bagi kelompok Islam fundamentalis menganggap kelompok Islam Liberal atau Islam Nusantara ini adalah sesat, jahat, dan jauh lari ajaran Islam sebenarnya. Karena mereka memisahkan kehidupan dengan agama. Begitu juga sebaliknya. Bagi kelompok Islam liberal-sekuler atau Islam Fundamental ini, mereka cap dengan kata/kata kelompok radikal, intoleran, anti kebhinekaan, anti Pancasila, hingga dikatakan sarang teroris yang mengancam keutuhan NKRI. Cuma bedanya, kelompok Islam Nusantara yang sekuler-liberal ini diback- up penuh oleh kekuasaan. Karena patuh dan tunduk pada penguasa hari ini. Beda dengan kelompok Islam fundamentalis, banyak para tokoh dan aktifisnya dipenjarakan dan dikriminalisasi. Kembali kepada judul tulisan di atas. Setelah Sukmawati ini, tentu kita berharap para pentolan penganut paham Islam nusantara atau Islam liberal-sekuler yang selama ini gigih dan getol membully Islam ? Segera menyusul dan mengikuti langkah Sukmawati. Dan justru menjadi murtad ini adalah solusi terbaik bagi para penganut Islamphobia. Dari pada jadi duri dalam daging bagi Islam dan keutuhan bangsa. Terlepas apa jenis agama baru yang mereka pilih. Atau bahkan tanpa agama saja sekalian alias anti Tuhan seperti ajaran Komunis-Atheis. Tak usah basa-basi lagi. Permasalahan konflik antara haq dengan batil, fundamentalis-radikal dengan paham sekulerisme-liberal ini, sebenarnya sudah ada sejak zaman para Nabi. Jadi kita tidak mesti gagap dan heran lagi. Bagaimana para Nabi ketika menyampaikan sebuah nilai kebenaran agama, malah dikriminalisasi, dibunuh, dianiaya, dibully, diusir, dipenjarakan, dan dituduh sebagai tukang bohong, tukang sihir, penjahat, teroris, dan pembohong. Termasuk melawan pada penguasa yang zalim. Jadi mari kita jaga bangsa ini dengan rasa cinta kebersamaan. Tidak dengan rasa dengki, dendam dan benci. Toleransi bukan harus saling mengikuti tapi saling menghormati. Kebhinekaan itu adalah satu dalam keberagaman yang hakiki bukan memaksakan kehendak untuk menyeragamkan. Radikal dan politik identitas itu adalah karakter dasar dan jati diri bangsa Indonesia yang beragam dan ta’at pada nilai spritual keagamaan. Bukan ancaman karena tidak tunduk pada kekuasaan. Selamat bagi Bu Sukmawati, semoga Indonesia tetap berjaya dalam keberagaman, dan para koleganya kita doakan segera menyusul. InsyaAllah.
Aku Banteng, Kamu Celeng, Mereka Pancasila, Apa Iya?
UNGKAPAN paling kasar ketika seseorang marah adalah celeng. Tingkatan di bawahnya adalah genjik (anak celeng), di bawahnya adalah anjing, di bawahnya lagi kirik (anak anjing). Ungkapan kasar yang diperhalus adalah anjrit, kamuflase dari kata anjing. Diksi kemarahan paling “sopan” adalah bangsat. Kata-kata kasar ini biasanya disemprotkan untuk merendahkan dan menghina musuh atau teman yang sedang bertikai. Celeng menjadi kata yang cukup populer beberapa hari ini. Jika kita lakukan survei sederhana di google, kata “PDIP Celeng” ditemukan 1.880.000 kata, “Ganjar Celeng” menghasilkan 2.770.000 kata, dan “Pendukung Ganjar Celeng” ada 138.000 kata. Umpatan celeng membanjiri pemberitaan dan menjadi populer setelah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah murka terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang secara masif blusukan ke berbagai daerah, bahkan sampai Papua. Kader banteng itu diduga membawa misi tersembunyi, yakni menarik simpati untuk pencapresan 2024. Sepak terjang Ganjar membuat PDIP blingsatan. Maklum PDIP sedang getol menyiapkan kader biologisnya, Puan Maharani untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Bambang makin tersulut pasca Albertus Sumbogo, Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Bambang menyebut kader PDIP yang tidak satu barisan dengan petuah Megawati, dicap sebagai celeng. Mereka tidak dianggap keluarga banteng, tetapi celeng. Anehnya yang diceleng-celengkan tidak marah. Padahal celeng adalah hardikan paling kasar dan hina bagi orang Indonesia. Perangai kasar tampaknya menjadi hal biasa bagi keluarga Banteng maupun Celeng. Lihat saja, sebelum ini kekerasan dipertontonkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga kader Banteng. Risma yang seharusnya tampil lembut dan anggun justru lebih senang mirip Gatutkaca edan. Bertolak pinggang dan menunjuk-nunjuk orang. Risma yang setiap katanya seharusnya merdu justru yang keluar suara parau dan berisik. Ini terjadi di dalam sebuah pertemuan di Kabupaten Gorontalo. Adalah pendamping PKH bernama Fajar Sidik Napu yang ketiban sial. Ia dimarahi Mensos dan ditunjuk-tunjuk oleh kader Banteng yang sedang emosi. Risma berjalan ke arah Fajar sambil berteriak, “Tak tembak kamu, tak tembak kamu,” ujar Mensos murka. Selang beberapa hari, di Lombok Timur, NTB, Menteri Risma juga ngamuk lagi. Kali ini terkait dugaan oknum kepala desa di Lombok Timur yang menjadi pemasok komoditas bantuan sosial. Risma berdebat keras dengan pendemo yang protes kenapa kepala desa bisa menjadi pemasok barang bansos (bantuan sosial). Dalam debat tersebut, Risma seperti biasanya bicara dengan keras dan lantang. “Kamu jangan fitnah aku ya! Sebentar dengerin!!!. Saya tidak akan ke sini kalau nggak ada niat baik selesaikan masalah, ngapain saya ke sini. Kedua, saya tidak tahu suplier atau tidak, saya ini menteri tidak urusi hal ini,” kata Risma ngamuk dengan kencang. Kekerasan ternyata tidak hanya merasuki banteng dan celeng. Akan tetapi, juga menular kepada aparat polisi. Sejatinya, mereka penegak hukum, bukan pelanggar hukum, apalagi membanting hukum. Masih segar diingatan rakyat, di bulan Oktober 2021, kekerasan beruntun dilakukan oleh anggota polisi. Kami tidak menyebut oknum, karena tidak ada tulisan kata itu di bajunya, maupun pada atribut lainnya. Polisi membanting mahasiswa hingga pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dirawat dua hari dua malam, saat berdemo di Tigaraksa, depan Kantor Bupati Tangerang. Hampir bersamaan waktunya, kekerasan juga terjadi di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di medsos, menunjukkan seorang pria dipukuli oleh anggota polisi lalu lintas hingga terkapar di jalan. Tampak, pria yang memakai jaket hitam tersebut tiba-tiba dipukuli oleh polisi. Wajah pria tersebut berulang kali ditampar. Pria tersebut tidak bisa melawan dan langsung terkapar di jalan. Kekerasan yang terjadi pada banteng dan celeng, ternyata juga merasuki aparat birokrat dan politisi. Gubernur Maluku, Murad Ismail misalnya, juga mengeluarkan kata-kata kasar saat menanggapi aksi demo tolak PPKM yang sering terjadi di Kota Ambon. “Jangan terpengaruh oleh itu apa, kaskadu kaskadu (kurap) itu yang cuma berapa ekor, tapi selalu buat…, sekali-sekali masyarakat Maluku kompak, kumpul la pukul mereka sampai tai keluar dari pantat,” kata Murad dalam sambutannya di Paroki Katholik Maria Bintang Laut, Ambon. Tidak hanya itu, seorang PNS di Lampung Selatan juga berkata kasar dengan mengucapkan kata-kata “Anjing Kau” serta kerap menggoblok-gobloki pegawai yang lain. Tabiat kasar juga dipertontonkan wakil rakyat. Beberapa tahun yang lalu anggota DPR Bambang Soesatyo yang kini menjadi Ketua MPR juga mengumbar kata 'lonte politik' untuk menyerang politikus Golkar pro Aburizal Bakrie yang pindah ke kubu Agung yakni Mahyudin, Airlangga Hartarto dan Erwin Aksa. Yang paling fenomenal adalah pernyataan Gubernur DKI ketika itu Basuki Tjahaja Purnama yang mengumpat dengan menggunakan 'bahasa toilet' saat wawancara live di TV. Dalam beberapa hari ini, rakyat Indonesia dipaksa mengonsumsi, kata-kata, perilaku, dan sikap kasar dari pejabat publik. Rasanya kita bukan hidup di negeri yang berketuhanan dan beradab. Kita mirip hidup di sebuah rimba yang tanpa aturan. Apakah sudah tidak ada lagi kelembutan tutur kata dari para pejabat? Misi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh para pejabat itu? Apakah mereka stres. Rakyat jauh lebih stres menyaksikan ulah rezim hari demi hari yang tidak menghiraukan kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Perilaku dan kata-kata kasar di era medsos tidak mungkin bisa disaring. Ia masuk ke gadget anak-anak, di sekolah, di rumah, di kamar tidur, dan di mana saja berada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti para orangtua supaya tidak terbiasa berkata kasar pada anak. Sebab, sekali membentak akan berakibat fatal terhadap perkembangan otak anak. Sekali saja anak usia dini dibentak, maka triliunan sel otaknya rusak. Anomali percelengan dan akrobat politik partai berlogo binatang itu, setidaknya telah memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Mereka tidak sadar, apa yang mereka lakukan sesungguhnya menunjukkan wajah asli dari mereka sendiri yang bengis, kasar, brutal, radikal, dan menang sendiri. Kita sebagai manusia beradab, sungguh prihatin dengan sepak terjang mereka. Ada berapa juta anak-anak yang menyaksikan polah kasar mereka. Kejadian ini mengingatkan kita betapa kekerasan semakin dekat dengan mata dan telinga kita. Kekerasan fisik, psikis, maupun verbal. Elite politik dan pendukungnya, diminta jangan mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan, dan memberikan teladan buruk kepada anak-anak. Bagaimana berikrar “Aku Pancasila”, jika setiap kata yang keluar dari lambenya adalah kata-kata kasar, kekerasan, dan penghinaan. Jauh dari adat dan adab. (*)
Penyesatan Logika (Logical Fallacy)
BANGSA ini dijajah, ditindas, dijarah, didzolimi, ratusan tahun oleh bangsa Eropah (Portugis-Spanyol- Belanda-Inggris) dan Jepang. Tapi, narasi yang dibangun saat ini adalah narasi kebencian terhadap bangsa Arab. Yang merusak dan menghancurkan negeri kita hari ini adalah ; budaya korupsi, konsumsi narkoba, gaya hidup materialistik dan hedonis, perampokan sumber kekayaan alam negara oleh elit oligharki, sex bebas, dan LGBT. Namun di spanduk beberapa seminar, upacara, sekolah, yang dianggap ancaman adalah ; Radikalisme, Intoleransi, Politik identitas. Oknum dan kelompok yang banyak merusak dan menghancurkan bangsa ini hingga banyak masyarakat yang miskin dan bodoh adalah : Politisi partai politik, aparat negara, cukong, dan pejabat. Tapi yang diprovokasi untuk dimusuhi seolah jadi musuh negara adalah ; Ulama, Kiyai, Habaib, Aktifis dan Pejuang Demokrasi. Yang secara fakta dan sejarah kelompok yang berkhianat, membunuhi rakyat dan mau mengganti Pancasila adalah ; PKI di zaman Soekarno, dan RUU HIP diusulkan PDIP di zaman Jokowi. Tapi yang selalu dituduh anti Pancasila dan dibubarkan ormasnya adalah ; FPI dan HTI. Yang selalu bohong, tidak menepati janji, membuat hutang dan perjanjian investasi merugikan negara hari ini adalah rezim penguasa. Tetapi yang dipenjarakan adalah para pejuang yang mengkritik dan mengingatkan untuk perbaikan. Demikianlah potret buram bangsa kita hari ini. Telah terjadi upaya penggeseran nilai moralitas dan nilai-nilai kebaikan menjadi terbalik. Nilai moralitas dan nilai-nilai kebaikan yang baik, disulap menjadi kata-kata yang menakutkan. Nilai kehidupan yang membawa dampak kerusakan dan maksiat, dipoles seolah menjadi nilai kebaikan atas nama moderenisasi dan kemajuan. Radikalisme (taat kepada ajaran agama yang mengakar), Intoleransi (ke-istiqomahan atas nilai moral individual), Politik identitas (Nilai kodrati dan fitrah atas keberagaman), disulap jadi kata-kata yang sangat buruk menakutkan. Padahal, Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada radikalisme terhadap agama dan keyakinan sehingga lahirlah semangat perlawanan berbasis nilai spritualitas yang tinggi. Padahal sikap intoleransi ini adalah benteng manusia secara individu atas nilai-nilai yang merusak nilai dan moralitas yang sudah ada hidup dan berkembang sesuai kearifan lokal nusantara. Namun intoleransi saat ini, menjadi alat “pemukul” kepada mereka yang tidak mau ikut dan tunduk pada nilai nilai kehidupan liberal dan sekulerisme. Sambil, melemahkan dominasi kelompok mayoritas agar tunduk dan takluk pada minoritas. Padahal politik identitas untuk kondisi keberagaman nusantara adalah karakter dasar yang harus dijaga, agar tidak larut dalam budaya budaya global yang merusak jati diri anak bangsa. Sehingga bangsa Indonesia tetap berkarakter Indonesia berjati diri nusantara yang religius. Begitu juga dengan isu “War on terror”, dimana di Barat isu ini sudah tak laku lagi dan basi. Karena barat khususnya Amerika sudah sadar dan kecolongan, ketika mereka sibuk tiga dasa warsa memerangi kelompok Islam di timur tengah, di satu sisi China bangkit sebagai negara naga raksasa baru dunia. Malah hari ini China negara komunis adi daya hari ini, sudah berani terang terangan menantang hegemoni Amerika dan sekutunya. Namun di Indonesia, aparat dan penguasanya semakin serius menjadikan isu terorisme untuk menghabisi kelompok Islam yang mayoritas di Indonesia. Islam berhasil mereka balik menjadi ancaman dan musuh negara berbasis Fasisme-Feodalistik. Yaitu ; Mengadu domba sesama ummat Islam, ummat Islam dengan kelompok non-muslim radikal, Islam Vs Syiah, Islam Vs Kelompok Sekuler/Liberal, dan Islam Vs musuh abadinya Neo-Komunis. Kelompok Islam yang tak mau tunduk akan di cap radikal, intoleran, ujungnya diteroriskan agar punya legitimasi untuk dihabisi. Tapi kelompok Islam yang manut, patuh, meskipun tolol dan idiot akan diberikan fasilitas kekuasaan dan jabatan. Sempurna sudah kelompok Islam yang taat (fundamental) dikeroyok kekuasaan dan antek-antek peliharaannya. Kondisi sosial hari ini kalau kita tanyakan kepada para tokoh sepuh dan orang tua memang sangat mirip sekali dengan suasana sosial politik ketika PKI berkuasa pada tahun 1960an di bawah kekuasaan rezim orde lama Soekarno. Ummat Islam dibuat gerah dan tidak nyaman hidup di negeri ini. Kriminalisasi, persekusi, penistaan, hingga pembunuhan sadis dialami ummat Islam saat itu. Ulama dan tokohnya dipenjarakan. Ajaran Islam dinistakan. Ormas pelindung ummat Islam yang idealis dibubarkan. Tapi sebaliknya para pembenci Islam dipelihara dan diback-up kekuasaan. Lalu apa bedanya dengan hari ini ??? Itulah yang disebut dengan perang asymetris berbasis ideologi. Menggunakan methode logical fallacie dalam hal mencuci otak masyarakatnya agar menjadi terbalik. Agar mudah disusupi, diracun pikirannya, dan kemudian dikuasai kehidupannya. Sebagai mana strategi komunis dalam menguasai sebuah negara yaitu ; Miskinkan, bodohi, pecah belah, hancurkan, kuasai, dan teror. Awalnya mereka akan angkat isu menjunjung tinggi nilai keberagaman agar tidak terjadi hegemoni kelompok mayoritas. Setelah itu masing kelompok yang beragam ini mereka pertentangkan dan ado domba hingga berpecah belah dan saling cakar. Kemudian baru mereka masuk dan kuasai sambil mengatakan agama sebagai sumber masalah yang melahirkan keberagaman, maka solusinya tinggalkan agama dan hidup jauh dari nilai agama yang dianggap sebagai racun dan candu. Awalnya sejalan dengan ideologi sekuler dan liberal yaitu memisahkan kehidupan dari agama dan hidup bebas dari nilai agama yang doktrin. Namun puncaknya adalah ; Mereka hidup tanpa agama, anti terhadap agama, dan tunduk hanya pada penguasa tunggal atas nama negara. Itulah puncak dari ideologi komunisme itu. Jadi sudah jelas bukan ?? Siapa musuh sejati bangsa kita hari ini ?? Jawabannya adalah kelompok Neo-Komunis yang disponsori negara super power baru China. China hari ini di bawah kepemimpinan Xi Jin Ping, akan menjadikan instrumen ideologi komunisme sebagai sarana mewujudkan impiannya menguasai dunia. Dan Indonesia adalah salah satu target utamanya. Menggunakan sentimen dendam para anak PKI yang gagal dua kali kudeta, memanfaatkan sentimen kebencian kelompok minoritas non-muslim radikal, memanfaatkan sentimen penganut Syiah dan kelompok Liberal untuk jadi ujung tombak proxy China untuk “soft-aneksasi” Indonesia menjadi Indochina 2030. Jawabannya sekarang ada pada seluruh rakyat Indonesia. Musuh sudah jelas di depan mata. Masih mau ditipu daya dan dibodohi? Masih jadi pengecut? Atau bangkit bersama melawan? Alias bangkit atau punah? Biarkan waktu yang menjawabnya. Wallahualam.
Meluruskan Pemikiran Agus Widjojo
WAJAR terjadi reaksi yang sangat keras dari banyak kalangan atas pernyataan Letjen Purn TNI Agus Wijoyo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI ke 8 tahun. Tidak terlalu dijelaskan, apakah pernyataan jenderal bintang tiga yang satu angkatan dengan Luhut Binsar Panjaitan ini (angkatan ‘70) adalah pernyataan hasil pikiran pribadi atau sudah menjadi kebijakan resmi Lemhannas RI sebagai lembaga negara. Kalau itu kebijakan resmi institusi, tentu publik khususnya DPR, akademisi, dan keluarga besar TNI bertanya-tanya, sejak kapan doktrin utama TNI manunggal bersama rakyat ini berubah? Apa dasar kajian akademisnya? Secara konstitusi, dan UU Pertahanan, baik pasal 30 UUD 1945 dan UU nomor 3 tentang Pertahanan, termasuk juga UU nomor 34 Tahun 2004 tentang Tupoksi TNI, masih dengan tegas tertulis bahwa : Jatidiri TNI adalah sebagai Tentara Rakyat (BAB II, poin 1 UU nomor 34 tahun 2004 Tentang Tupoksi TNI). TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara (UU nomor 3 Tahun 2002), juga menyatakan bahwa TNI menganut sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata), dimana apabila terjadi ancaman baik dari dalam dan luar negeri, maka TNI bersama rakyat bersatu padu, menggunakan semua potensi sumber daya nasional yang ada maupun buatan untuk melakukan perlawanan serentak. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 30 tentang kewajiban bela negara bagi setiap penduduk dan seluruh rakyat Indonesia. Secara hakikat ancaman, yang termaktub di dalam buku putih pertahanan nasional Indonesia, baik itu ancaman nyata dan tidak nyata, ancaman yang ada dan yang akan ada, sampai dengan penggolongan jenis ancaman mulai dari ancaman symetris (fisik), ancaman asymetris (non-fisik), dan ancaman hybrida (gabungan fisik dan non-fisik), sebagai negara yang begitu luas dan heterogen tentu dibutuhkan sebuah sistem pertahanan yang tangguh, handal, efektif, terintegrasi dan berkesinambungan. Makanya, berdasarkan sejarah historikal, pengalaman, dan filosofis suasana kejiwaan masyarakat Indonesia yang majemuk, para senior pendahulu Tentara Nasional Indonesia mulai dari era Panglima Besar Jendral Soedirman, Gatot Subroto, Jendral AH Nasution, dan Soeharto, menjadikan konsep Kemanunggalan TNI ini sebagai doktrin utama yang wajib diimplementasikan. Sehingga secara personal, kemanunggalan TNI bersama rakyat ini termaktub dalam sumpah Sapta Marga Parjurit TNI dan Delapan Wajib TNI. dimana secara implementasinya, konsep Sishankamrata ini direalisasikan dalam bentuk gelar kekuatan TNI melalui pembinaan Teritorial secara berjenjang mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa sebagai ujung tombak TNI di tengah masyarakat. Dengan hadirnya TNI di tengah masyarakat berupa pembinaan teritorial inilah, akan menjadi kekuatan pertama daya tangkal TNI dalam pertahanan dan keamanan nasional mengatasi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan), sesuai dengan pasal 6 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang Tupoksi TNI. Artinya, kemanunggalan TNI bersama rakyat ini adalah ruh dan napas kekuatan utama TNI. Kemanunggalan TNI bersama rakyat dimana Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI secara teologis boleh dikatakan “Akidah Dasar” seorang prajurit TNI, yang juga dijamin oleh konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Jadi apabila ada orang, personal, prajurit TNI baik itu yang masih aktif maupun sudah purna tugas, menafikan itu semua, maka sangat perlu dipertanyakan apa motif dan agendanya terhadap bangsa dan negara ini, khususnya TNI. Komentar Agus Widjojo (selanjutnya kita sebut AW), boleh dikatakan sangat salah kaprah, sesat pikir, atau lebih ekstrimnya lagi bisa dikatakan “murtad “ secara akidah dan doktrin TNI. Setelah ditelusuri, ternyata AW sejak masa dinasnya selalu getol menyuarakan bagaimana menghapuskan KoTer (komando teritorial) TNI AD ini dengan berbagai macam alasan. Pernah juga AW melemparkan isu kontroversial “rekonsiliasi dengan keluarga PKI”, dan sekarang mengatakan bahwa adalah salah pemahaman dan tidak ada istilah doktrin TNI manunggal bersama rakyat. Parahnya lagi mengatakan rakyat adalah milik Presiden. TNI juga adalah milik Presiden dengan alasan Presiden dipilih rakyat dan Indonesia adalah negara demokrasi. Anggota DPR Fadli Zon dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar sampai menganalisa ada semacam agenda terselubung atau “doktrin licik” yang mau AW paksakan untuk tujuan politik tertentu. AW menggunakan posisi dan jabatannya sebagai Gubernur Lemhannas RI, untuk menjustifikasi pikiran dan doktrin baru yang mau dia ciptakan. Walaupun itu sangat bertentangan dengan akidah doktrin TNI. Pemahaman AW ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI khususnya bagi TNI. Karena kemanunggalan TNI bersama rakyat ibarat tonggak utama sistem pertahanan negara kita. Lalu tonggak ini yang mau AW robohkan dan hapuskan. Ke mana arah pikiran dan agenda AW ini bagi yang paham sudah akan tahu mau ke mana. Makanya wajar juga, sampai ada keluarga besar TNI yang mengatakan, pemahaman AW ini bisa di kategorikan sebagai ancaman ideologis dan ancaman struktural yang sangat berbahaya bagi kedaulatan dan pertahanan negara kita. AW harus segera menjelaskan kepada publik apa dasar pemikiran dan ucapannya itu di acara mata najwa. Apakah itu ungkapan pribadi atau institusi? Kita juga berharap, Presiden, Menkopolhukam, Menhan, dan Panglima TNI juga melakukan evaluasi dan konfirmasi terhadap AW. Kalau perlu copot terlebih dahulu dari jabatannya untuk memudahkan proses penyelidikan seperti yang dialami Brigjen Junior Tumilaar. Statemen AW sungguh sangat disayangkan, dan menyakitkan bagi keluarga besar TNI. Alasan reformasi TNI bukan berarti jadi alasan untuk merusak akidah dan doktrin utama TNI. Itu namanya khianat dan murtad. Kemanunggalan TNI bersama rakyat adalah amanat suci dari para pendahulu kita yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Karena kemanunggalan TNI dan rakyat inilah negara ini bisa berdiri dan berhasil memadamkan berbagai bentuk pemberontakan, dan melakukan cegah dini, tangkal dini, terhadap berbagai bentuk ancaman. Lalu, mau diubah begitu saja oleh seorang AW? Atau AW sebenarnya juga hanya sebagai corong semata? Atau AW hanya melakukan “testing by water” terhadap soliditas TNI? Karena lagi rame-rame mau pemilihan Panglima TNI dan penunjukan jabatan Kepala staf yang baru? Kita semua tidak tahu sampai AW dengan gentleman menjelaskan maksud ucapannya kepada publik. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan anggapan liar dan penuh curiga terhadap AW yang kontroversial. Biarkan waktu yang menjawabnya. Yang jelas, TNI berada di bawah asas supremasi sipil sebagai amanah reformasi kita sudah sepakat meskipun masih perlu evaluasi. Pemahaman politik TNI adalah politik negara yang tunduk pada konstitusi UUD 1945 negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan juga negara hukum juga sudah selesai. Tapi jangan coba-coba giring seolah TNI adalah milik presiden yang kemudian diartikan TNI harus tunduk pada presiden secara vertikal dan tunggal. Ini berbahaya. Karena TNI akan mudah dijadikan sebagai alat kekuasaan dan politik partisan. TNI berada di atas semua golongan, dimana TNI sebagai anak kandung rakyat, akan selalu utama mementingkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan kekuasaan (penguasa). TNI tunduk pada asas supremasi sipil, tapi bukan berarti TNI bisa dikendalikan dan dikuasai kepentingan politik kelompok. Dan kemanunggalan TNI bersama rakyat adalah formulasi ampuh, agar TNI berpolitik negara, bukan politik praktis. Agar TNI setia kepada rakyat dan konstitusi, bukan pada kepentingan elit penguasa. Itulah jatidiri TNI. Insya Allah.
Pisahkan TNI dari Rakyat, Otak Agus Widjojo Kerasukan Paham Komunis.
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo sedang kerasukan paham komunis. Bisa juga ia sedang kerasukan sistem pemerintahan di negara monarkhi atau kerajaan. Narasinya, rakyat itu punya presiden, bukan punya Tentara Nasional Indonesia (TNI) apalagi punya Panglima TNI, sangat menyakitkan tentara dan rakyat. Itu tidak lain karena ucapannya yang memelintir pemisahan antara TNI dengan rakyat. Purnawirawan berpangkat letnan jenderal itu memiliki pemahaman yang dangkal mengenai hubungan TNI dan rakyat. Dia tidak mengerti, sejak dahulu kalau rakyat itu menjadi pejuang dalam berusaha merebut kemerdekaan Indonesia. Agus Widjoyo pantas mendapat hujatan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama TNI yang selama ini bahu-membahu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pun juga saling bahu-membahu merawat dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Gubernur Lemhanas menyampaikan kata-kata nyeleneh. Hal itu dilakukannya setelah Brigadir Jenderal Junior Tumilaar, saat menjabat sebagai Inspektorat Komando Daerah Militer (Irdam) XII Merdeka mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang intinya membela Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang dipanggil aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado, Sulawesi Selatan. Itinya, Junior keberatan pihak kepolisian memanggil anggota Babinsa dalam kasus pelaporan lahan milik antara Ari Tahiru (penduduk setempat) dengan PT Ciputra Internasional. Junioar tidak rela anggota Babinsa dipanggil polisi. Nah, kembali ke narasi Agus yang menyebutkan, rakyat adalah milik presiden, bukan TNI apalagi panglima TNI, jelas sangat bertentagan dengan konsep-konsep kemanunggalan TNI dan rakyat. Menurut Agus, rakyat dan TNI itu hanya menyatu dalam perang. "Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara, jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," kata Agus Widjojo seperti dalam tayangan channel Youtube Najwa Shihab. "Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, begitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik," ujarnya. "Nah waktu perang, itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi, setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, Pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima," lanjutnya. "Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat. Juga kepada sumber daya sipil di masa damai, TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range," kata Agus Widjojo. "Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI-rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi, artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak," jawab Agus Widjojo. Itulah antara lain kalimat-kalimat yang dikutip dalam wawancara antara Nazwa Shihab dengan Agus. Ia terus berusaha memisahkan TNI dengan rakyat. Padahal, sejak awal TNI itu berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Agus mengatakan, perjuangan merebut kemerdekaan adalah perjuangan politik. Dia lupa, dalam perjuangan itu ada perjuangan angkat senjata, perjuangan politik dan diplomasi. Akan tetapi, jika membaca sejarah, perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang dijajah Belanda dan Portugis selama 350 tahun, serta Jepang 3,5 tahun, jelas lebih banyak didominasi perjuangan fisik atau angkat senjata. Ingat perjuangan Tuanku Imam Bonjol, Sisingamangaraja XII yang bergelar Patuan Besar Tuanku Oppu Batu, Pangeran Diponegoro, Ahmad Pattimura, Fatahillah, dan sederet nama lainnya yang diabadikan menjadi Pahlawan Nasional. Kok Agus Widjojo sudah mulai pikun, sehingga melupakan sejarah perjuangan rakyat. Mungkin otaknya sudah kental dengan paham komunis dan kerajaan, sehingga semuanya milik presiden (di negara komunis) dan milik raja (di kerajaan). Apakah sebagai anak seorang Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswodihardjo wajar memutar-balikkan sejarah dan fakta. Coba baca sejarah lagi. Sebelum merdeka, betul perjuangan dilakukan oleh pejuang-pejuang nasional, terutama ulama yang memimpin beberapa laskar. Nah, setelah merdeka, kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Inilah cikal bakal TN. Pada 5 Oktober 1945, BKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Namanya, selalu menggunakan kata rakyat, sebelum akhirnya pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi. Sejarah kemudian mengubah TNI menjadi Angkatan Perang Republik Serikat (APRIS), seiring dengan berubahnya Indonesia menjadi negara federasi, Desember 1949 dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketika RIS dibubarkan 17 Agustus 1950, maka APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Tahun 1962, dilakukan penyatuan angkatan perang dengan kepolisian negara, sehingga menjadi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Betul selama orde baru ada kesalahan dalam menerapkan Dwifungsi ABRI. Konsep yang diletakkan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution disalahgunakan oleh Jenderal Besar Seoharto guna melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden. Akhirnya, Seoeharto dan Nasution yang sama-sama berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) bermusuhan. Akan tetapi, Dwifungsi tersebut berakhir seiring dengan jatuhnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan Indonesia. ABRI dikembalikan menjadi TNI. Kemudian TNI pun dipisahkan dari Kepolisian RI. Kembali ke pernyataan Agus Widjojo itu. Jelas narasinya salah. Sekali lagi, rakyat adalah milik presiden adalah narasi yang bisa dikembangkan di negara komunis dan monarkhi. Bukankah sekarang ini sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Eropah justru mulai menerapkan perang grilya. Sebuah konsep perang yang ditulis Jenderal Abdul Haris Nasution dalam buku, “Perang Gerilya” yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Perang gerilya adalah sebuah pertempuran yang ‘melibatkan’ rakyat. Rakyat biasanya memberikan bantuan dalam beberapa hal, seperti waktu perang kemerdekaan. Perang gerilya adalah sebuah taktik menyatukan tentara dengan rakyat. Banyak hal yang positif bersatunya TNI dengan rakyat. Di masa orde baru ada Abri Masuk Desa (AMD). Tentara bersama rakyat membangun fasilitas desa, misalnya membangun jalan, membangun irigasi, dan fasilitas lainnya. Sekarang, hal itu masih berlanjut dengan nama Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Baik AMD dan TMMD, sama-sama melibatkan personil dari Angkatan Darat, Angkatan Udaran dan Angkatan Laut. Sewaktu AMD, tentu dengan tambahan dari aparat kepolisian, karena masih menyatu dengan ABRI. Harus diakui, tidak selamanya Babinsa itu baik. Demikian juga aparat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polri. Babinsa dan Binmas sama-sama bisa disalahgunakan. Keduanya bisa dianggap memata-matai kegiatan rakyat, terutama mereka yang berada pada kubu oposisi. Tentu kita juga sepakat, kelakuan Babinsa di masa orde baru tidak diperlukan sekarang. Contoh kelakuan Babinsa yang sangat buruk dan mencederai umat Islam adalah ketika Sertu Hermanu, Babinsa di Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berpatroli di wilayahnya, pada 7 September 1984. Ia menemukan pamplet anti pemerintah di musala As Saadah. Ia kemudian menyambangi sang pengurus, dan meminta agar pamplet-pamflet tersebut disingkirkan. Dikabarkan, ia mencopot sendiri pamplet tersebut. Bahkan, isunya, ia menyiram dengan air got, dan tanpa membuka sepatu masuk ke musala itu. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusuhan yang terkenal dengan Peristiwa Tanjung Priok yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan korban luka.
Setelah Islam, Sekarang TNI, Masih Belum Percaya Ancaman Komunis?
TENTU banyak yang bertanya kenapa rezim hari ini begitu “tidak ramah” terhadap Islam. Meskipun ummat Islam sebagai mayoritas dan pemilik saham terbesar atas berdirinya negara ini, tapi diperlakukan seperti terasing di negerinya sendiri. Penyakit Islamfobhia di negeri ini begitu parah dan menyakitkan. Atas nama fitnah radikalisme, intoleransi, dan politik identitas, rezim hari ini bersama buzzer dan jajarannya seakan mendapat privilege khusus untuk bisa berbuat apa saja terhadap Islam. Mulai dari pelarangan cadar, stigma buruk celana cingkrang, bendera Laillahaillallah yang berupa kalimat suci ummat Islam sedunia distigmakan sepihak sebagai lambang teroris. Pelajaran dan kurikulum agama dihapuskan (meski sempat direvisi), kearifan lokal berbau syariat Islam melalui Peraturan Daerah ratusan jumlahnya dicabut. Dana haji nya tak jelas keberadaan dan laporannya, sudah dua tahun ummat Islam Indonesia tidak bisa naik haji dengan alasan Covid-19. Para ulama dan aktifisnya dipenjarakan. Organisasi atas nama Islam seperti FPI dan HTI dibubarkan dengan alasan yang dibuat-buat. Hari ini, seolah ummat Islam menjadi beban buruk bagi bangsa ini. Ada yang ngaku ulama, pakai sorban, bergelar Kiyai, dan malah menjabat ormas Islam yang besar, tapi komentar dan celotehnya lebih banyak menyakitkan hati ummat Islam. Bahkan menjurus pada pelecehan, seperti bilang Allah itu tidak ada dalam Al Quran. Kalau ada para Ulama, Habaib, Kiyai, aktifis yang melakukan pelurusan dan pencerahan terhadap pemahaman Islam dan stigmaisasi negatif terhadap Islam, malah dituduh Ustad radikal, ulama intoleransi, tidak cinta NKRI, dan anti keberagaman. Begitu mudahnya kelompok rezim hari ini membolak-balikkan fakta menggunakan instrumen kekuasaan. Negara ini seolah menuju negara Fasisme. Siapa yang ikut dan tunduk pada negara, maka akan dapat jabatan, fasilitas, dan kekuasaan. Tapi siapa yang tidak mau ikut dan tunduk, maka bersiap siaplah dengan resikonya. Ternyata tidak sampai disitu saja. Hari ini, aura kebencian dan permusuhan juga “mulai terjadi dan bergeser” terhadap keluarga besar TNI. Dimulai dari ditangkapnya Mayjend Purn TNI Kivlan Zen, Mayjend Purn Sunarko, konstalasi politik mulai semakin tendensius. Kenapa mulai tendensius? karena sudah mulai berani menyebutkan ada purnawirawan TNI dengan kata kata Radikal. Belum lagi survey dari Kemenag yang menyatakan ada 5 persen anggota TNI aktif yang terpapar radikalisme. Setelah itu, terjadi lagi penangkapan terhadap Kapten Ruslan Buton yang menyuarakan suara rakyat melalui surat terbukanya kepada Presiden. Dimana sebelumnya Kapten Ruslan Buton membongkar bagaimana aktifitas TKA China di Maluku utara yang dalam kaca mata insting militernya sudah sangat mencurigakan dan jadi ancaman bagi kedaulatan negara. Yang terbaru, viralnya surat terbuka Bigjen TNI Junior Tumilar, Irdam Kodam Merdeka, yang membuat surat terbuka kepada Kapolri, atas pemeriksaan anggota Babinsa oleh Polres dan penyerobotan lahan sepihak oleh perusahaan atas tanah adat masyarakat setempat. Namun sayang, Jendral bintang satu ini juga bernasib naas. Beliau dicopot dari jabatannya atas alasan untuk memudahkan pemeriksaan. Yang sekarang sedang ditangani Puspomad TNI AD. Terakhir (sampai tulisan ini ditulis), bagaikan petir di siang bolong, tiba-tiba Gubernur Lemhannas Letjen Purn TNI Agus Widjojo mengeluarkan statemen kontroversial di acara Mata Najwa. Dimana dalam pernyataannya, Agus mengatakan bahwa ; seolah tak ada sebenarnya doktrin tentara manunggal rakyat. Atau istilah pertahanannya, konsep Binter (pembinaan teritorial) hanyalah akal-akalan era Soeharto biar tentara enak-enak sebagai penopang kekuasaannya. Sontak pernyataan Agus yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Lemhannas membuat para TNI aktif maupun purnawirawan meradang dan marah. Karena, konsep Binter adalah bagian dari implementasi Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) yang dijamin konstitusi serta sudah teruji handal, tangguh sebagai konsep pertahanan rakyat yang menghantarkan rakyat ini merdeka dan bisa memadamkan berbagai pemberontakan dalam negeri. Konsep Binter di mata Agus seolah lahir dari tentara yang malas mikir. Padahal, konsep Binter ini adalah salah satu ide jenius dan brilian dari para senior TNI mulai dari Jendral Soedirman, Gatot Subroto, Dan AH Nasution. Menyatunya rakyat dan TNI teruji menjadi instrumen daya tangkal yang ampuh dalam upaya cegah dini, tangkal dini dalam menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) Justru konsep Sishankamrata inilah yang menjadi ruh utama kekuatan TNI saat ini. Dimana konsep ini boleh dikatakan konsep yang paling ditakuti oleh pihak yang ingin menguasai Indonesia. Jadi sangat aneh, seorang Gubernur Lemhannas yang informasinya tidak pernah sekolah Lemhannas ini mengeluarkan statemen seperti itu. Agus Wijoyo seakan menyampaikan kegelisahan suatu kelompok selama ini yang merasa terganggu dengan keberadaan TNI di tengah masyarakat melalui fungsi teritorial ini. Karena fungsi teritorial TNI juga adalah mata dan telinga TNI di tengah masyarakat. Kejadian yang menimpa Brigjen Junior Tumilar, Kapten Ruslan Buton, Mayjen Kivlan Zen, adalah salah satu bentuk bagaimana secara personal ketika prajurit TNI yang Saptamargais itu tahu akan sumpah dan delapan wajib TNI nya, tidak akan khianat, tidak akan diam, tidak akan takut atau tunduk kepada siapapun ketika bangsa dan negaranya dalam ancaman. Tentara Indonesia itu lahir sebelum negara ini ada. Makanya disebut sebagai “ Tentara Rakyat “. Dengan jargon, Bersama Rakyat TNI Kuat. Karena TNI lahir dari rakyat untuk rakyat. TNI adalah anak kandung rakyat. Dan NKRI ini lahir oleh perjuangan rakyat dan tentara. Kok lupa jendral? Makanya juga, politik TNI itu adalah politik negara. Dimana konstitusi adalah sebagai Panglima Tertinggi. Sesuai Sapta Marga prajurit TNI. Jadi wajar pernah terjadi insiden dimana Panglima Besar Jendral Soedirman menentang perintah Soekarno yang memilih menyerah pada Belanda. Jenderal Soedirman memilih melanjutkan perlawanan gerilya bersama rakyat demi tetap tegaknya NKRI secara hukum internasional. Artinya, doktrin TNI sangat berbeda dengan doktrin negara lainnya di dunia. Kemanunggalan TNI bersama rakyat adalah kekuatan utama Sishankamrata. Kenapa ada yang takut dan risih dengan konsep ini? Ummat Islam dan TNI hari ini, boleh di katakan bernasib sama, dalam berada posisi yang sungguh sangat miris dan tersudutkan secara ideologis dan doktrin (Tupoksi). Kalau ada bahagian dari ummat Islam ataupun personil TNI yang mengatakan bangsa kita hari ini dalam keadaan baik-baik saja, berarti mereka itu adalah bahagian dari kerusakan hari ini. Sekarang pertanyaannya ada kembali kepada ummat Islam dan TNI. Apakah akan tetap diam? Takut? Menutup mata? Atau berkhianat? Jawaban ada pada diri masing-masing. Ancaman itu sudah nyata ada di depan mata. Ancaman bagi keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Sebuah ancaman yang menyusup masuk ke dalam sendi bernegara kita hari ini. Hanya bagi yang beriman dan punya jiwa sapta marga yang kuat (bagi TNI) yang bisa membaca semua ini. Sebagaimana takdir lahirnya haq dan batil. Baik dan buruk. Dimana sebuah kata bijak selalu mengingatkan kita semua. “ Apabila suatu bangsa melupakan sejarah kelam bangsanya, maka akan dikutuk untuk mengulangi sejarah kelam itu kembali “. Ingat, sejarah 1965 terjadi karena Soekarno melupakan sejarah 1948. Artinya kita semua hari ini jangan sampai melupakan sejarah 1965, agar sejarah kelam itu tidak terjadi kembali hari ini atau sebentar lagi. Wallahualam.