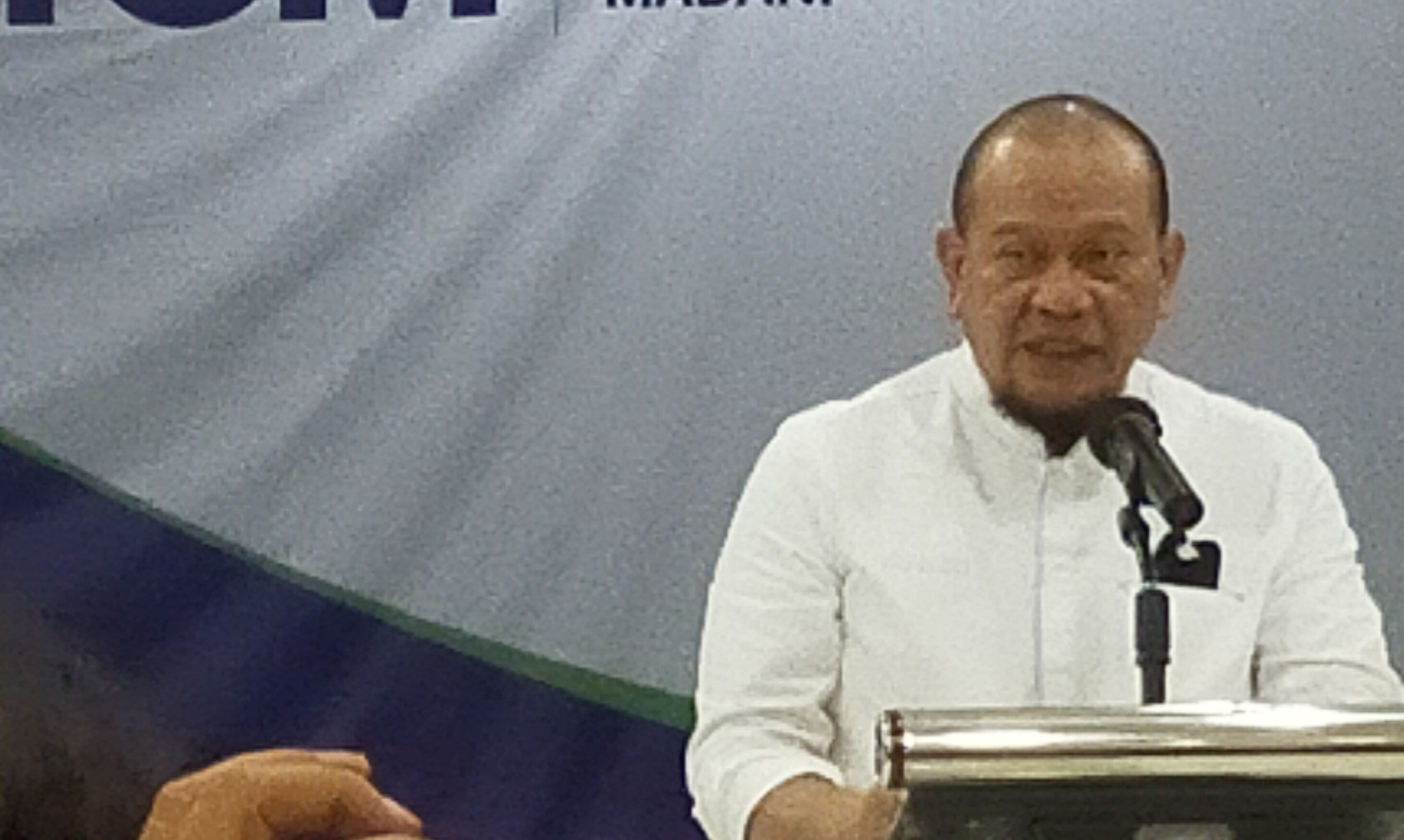POLITIK
Bu Mega Harus Berkeras: Puan Capres 2024, Prabowo Cawapresnya
By Asyari Usman Medan, FNN - Dalam tulisan terdahulu, Jokowi diskenariokan tiga periode. Prabowo Subianto (PS) akan menjadi cawapresnya. Skenario ini sedang digarap serius. Kemarin, barisan relawan yang menamakan diri Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024) resmi dibentuk. Gagagasan Jokowi tiga periode dengan Prabowo sebagai cawapres, mau tak mau, menimbulkan gesekan langsung ke Bu Megawati (ketum PDIP). Sebab, Bu Mega telah menyiapkan formula pencapresan Prabowo-Puan atau Puan-Prabowo. Tetapi, keinginan Bu Mega ini diganggu oleh orang-orang yang terlibat dalam survei elektabilitas. Misalnya, saat ini sedang deras opini yang melemahkan semangat Bu Mega untuk menjadikan Puan Maharani sebagai capres PDIP di Pilpres 2024. Yang terbaru adalah serangan Denny JA (DJA) yang menyimpulkan bahwa PDIP akan kalah kalau mengajukan Puan sebagai capres. Danny juga mengatakan, Ganjar Pranowo punya peluang besar menjadi ketum PDIP jika dia menang pilpres. Gagasan Denny ini sangat merendahkan. Meskipun Puan tak muncul signifikan di berbagai survei, tidaklah elok kalau itu dikatakan secara terbuka. Bu Mega harus “membungkam” DJA dengan cara yang membuat dia “mabuk” dan balik mendukung Puan. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tidak perlu berkeringat-keringat. Juga tidak perlu mengerahkan buzzer untuk mengeroyok Denny. Panggil saja Danny untuk bincang-bincang santai. Di rumah atau di plaza sate. Ajak dia bersaudara. Kasih dia kisi-kisi tentang “persaudaraan” itu. Dia pasti segera menangkap apa maksudnya. Pupuk persaudaraan “setebal” mungkin. Semakin tebal, makin mantap langkah DJA untuk menunjukkan persaudaraan dengan Bu Mega dan Puan. Itu tentang Denny JA. Yang juga mengerdilkan Puan adalah kemunculan relawan Jokpro 2024 seperti dijelaskan di atas. Salah satu pentolah Jokpro 2024 adalah M Qodari. Dia direktur lembaga survei, Indo Barometer. Nah, seperti halnya pendekatan dengan Denny, Bu Mega juga pasti bisa mengajak Qodari bersaudara. Dia bisa dirangkul untuk mengamankan Puan di Pilpres 2024. Tanya langsung Qodari “apa” yang dia perlukan. Klarkan segera. Fokuskan pandangan Qodari ke satu “benda keramat” yang akan membuat dia terhipnotis. Setelah itu, bakal muluslah jalan Mbak Puan. Selain DJA dan Qadari, banyak lagi yang harus diajak bincang-bincang dan membangun “persaudaraan tebal” demi memperkuat Puan menuju Pilpres 2024. Rekrut para aktivis survei lainnya, yang alsi maupun yang abal-abal. Tebalkan segala sesuatu untuk mereka. Pasti popularitas Puan akan melambung tinggi. Ini harus dilakukan oleh Bu Mega. Sekaranglah saatnya menyelamatkan Puan. Tidak banyak waktu untuk disia-siakan. Bu Mega harus berkeras agar Puan capres 2024. Yakinlah, Prabowo siap menjadi cawapres dengan dukungan penuh Gerindra. Perkara sudah ada janji Bu Mega mendukung Prabowo sebagai capres 2024, bukan masalah besar itu. Pak Prabowo akan selalu siap menerima apa saja. Beliau sudah biasa seperti itu. Jangan khawatir. Kalau Bu Mega tidak berkeras ajukan Puan sebagai capres 2024, konsekuensinya sangat fatal. Pertama, karir politik Puan akan tamat. Kedua, PDIP bakal diambil orang lain dengan mudah. Setelah 2024, generasi PDIP akan berubah. Tantangan dan tuntutan akan berbeda. Posisi Bu Mega akan melemah secara natural. Jadi, Pilpres 2024 adalah momen terbaik dan terakhir untuk Mbak Puan. Tidak akan ada lagi. Mumpung Bu Mega masih 100% menguasai PDIP, pastikan di internal partai bahwa Puan capres dan Prabowo cawapres. Hanya dengan formula inilah Bu Mega bisa mencegah Jokowi tiga periode dan sekaligus menyelamatkan Puan. Ingat, Pak Jokowi itu sangat kuat meskipun tidak punya partai. Beliau bisa bergerilya di DPR dan DPD untuk mengubah pasal 7 UUD agar presiden bisa tiga periode. Kecuali Bu Mega memang mendukung Jokowi tiga periode. End of discussion, tidak perlu diskusi lagi.[] (Penulis wartawan senior FNN.co.id)
Pemprov Banten Diminta Kaji Ulang Pinjaman Daerah
Serang, FNN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Nawa Said Dimyati meminta pemprov setempat mengkaji ulang terkait dengan rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun. "Terkait dengan adanya kebijakan baru mengenai adanya bunga pinjaman oleh PT SMI, harus dikaji ulang karena harus melihat kemampuan keuangan daerah agar nantinya tidak membebani APBD Banten," kata Nawa Said Dimyati dalam diskusi "Pojok Aspirasi DPRD Banten" di Serang, Sabtu (12/6). Latar belakang pinjaman kepada PT SMI yang dilakukan Pemprov Banten, lanjut dia, sama seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia, yakni dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COViD-19. "Rencana ini sejak 2020 yang akan meminjam RP4,9 triliun. Nah, pada tahun 2020 sudah terealisasi sekitar Rp800 miliar dan tidak ada masalah," kata politkusi Partai Demokrat ini. Menurut Nawa Said, yang menjadi persoalan adalah PT SMI sebelumnya tidak ada bunga dalam pinjaman itu namun tiba-tiba ada bunga. Ia mengemukakan bahwa pinjaman itu sebelumnya bisa dalam jangka waktu 10 tahun, sekarang maksimal 5 tahun. "Ini yang membuat Pemprov Banten perlu melakukan kajian kembali dan konsultasi publik agar nantinya pinjaman ini tidak ganggu APBD," kata Nawa Said. Pada awalnya, kata dia, pengajuan pinjaman itu DPRD memberikan pendapat karena hitungan dari sisi kemampuan fiskal tidak mengganggu APBD jika dengan jangka pembayaran pinjaman 10 tahun. "Ada program-program yang sebelumnya direncanakan dibiayai dari pinjaman PT SMI dan sudah mulai lelang. Ini juga yang bikin masalah," katanya. Selain menghitung lagi kemampuan anggaran untuk cicilan bayaranya jika kurang dari 10 tahun, kata dia, kemudian harus mendapatkan fatwa hukum dari pengacara negara. Rencana pinjaman PT SMI sebesar Rp4,1 triliun, lanjut dia, akan dianggarkan untuk membiayai layanan dasar di Pemprov Banten sebesar Rp77,4 miliar untuk Dinas Pendidikan, Dinas PUPR Rp1,6 triliun, Dinkes Rp1,01 triliun, Dinas Perkim Rp700 miliar, dan Disperindag sekitar Rp30 miliar. "Saya secara pribadi dan anggota DPRD menyerahkan penuh semuanya kepada pemprov dengan memperhatikan kemampuam bayar," kata Nawa Said. (sws)
Bupati Aceh Barat: Wacana PPN Sembako Ancam Stabilitas Nasional
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli M.S. mengkhawatirkan wacana Kementerian Keuangan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) di Tanah Air akan mengancam stabilitas nasional di tengah pandemi COVID-19. "Sebaiknya wacana pengenaan PPN sembako tidak dilakukan karena hal ini dikhawatirkan akan timbulkan gejolak di tengah masyarakat. Wacana ini berbahaya," kata Ramli M.S. di Meulaboh, Sabtu (12/6). Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR RI, salah satu di antaranya mengenakan PPN terhadap sembako. Menurut Ramli, berdasarkan berbagai masukan yang diterima oleh pemerintah daerah dari kalangan masyarakat, wacana tersebut akan menyebabkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain karena ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, katanya lagi, pengenaan PPN terhadap sembako juga akan berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dia memandang perlu meniadakan kebijakan tersebut karena masyarakat akan melakukan protes atau unjuk rasa. "Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar menolak rencana pengenaan PPN ini. Jika hal ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi gejolak di tengah masyarakat," kata Ramli menegaskan. Di sisi lain, Ramli MS mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah mencari sumber baru pengenaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. "Sebagai pejabat negara di daerah, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Bapak Presiden. Kami selalu siap mengawal dan menjalankan setiap perintah Presiden," kata Ramli. (sws)
Perlu Amandemen UUD 45 Jika Ingin Capres Independen
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 jika ingin membuka peluang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen pada pemilu. "Wacana tentang pasangan calon presiden/wapres independen memang sudah cukup lama mengemuka. Namun, hal itu terkendala adanya ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu. Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Menurut Titi, sebenarnya soal calon independen ini tak perlu terlalu jadi persoalan kalau ada skema yang lebih leluasa untuk pencalonan presiden/wapres melalui penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden berupa 20 persen kursi atau 25 persen suara hasil pemilu anggota legislatif. Paling mendesak itu, kata dia, sebenarnya saat ini pembuat undang-undang menghapus persyaratan ambang batas pencalonan tersebut sehingga peluang lahirnya calon-calon alternatif menjadi lebih terbuka lebar. "Kalau calon independen, mau tidak mau harus mengubah konstitusi," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Namun, lanjut Titi, kalau penghapusan ambang batas pencalonan, hanya pada level perubahan undang-undang tanpa perlu mengubah UUD NRI Tahun 1945. Titi yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan pasangan calon presiden/wapres dari jalur perseorangan. La Nyalla mengatakan bahwa DPD yang merupakan utusan seluruh daerah di Indonesia idealnya bisa menjadi saluran bagi putra/putri terbaik bangsa nonpartisan yang ingin maju sebagai calon presiden/wakil presiden dari jalur perseorangan. "Saya setuju dengan adanya wacana amendemen konstitusi ke-5 demi perbaikan dan koreksi atas perjalanan amendemen pertama hingga keempat mulai 1999 hingga 2002," kata La Nyalla di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (24/5). Dengan demikian, jalur perseorangan atau nonpartai politik bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi pilpres. La Nyalla mengatakan bahwa hanya parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tertutup saluran bagi putra/putri terbaik di luar kader partai atau mereka yang tidak bersedia menjadi kader partai. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "Ini ambiguitas dan paradoksal," katanya ketika tampil sebagai pembicara utama dalam focus group discussion (FGD) bertema "Amendemen Ke-5 Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold" di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Disebutkan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "Lalu mengapa untuk menjadi kepala pemerintahan, dalam hal ini untuk menjadi calon presiden, harus anggota atau kader partai politik saja?" katanya. La Nyalla melanjutkan, "Itu pun tidak semua partai bisa mengusung kadernya karena adanya presidential threshold." (sws).
Ketua DPDRI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang PPN Sembako
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan dan kebutuhan pokok atau sembako demi mendukung kesejahteraan masyarakat. “Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil,” kata Ketua DPD LaNyalla di Jakarta, Jumat. Ketua DPD LaNyalla mengatakan pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan berpotensi menaikkan biaya sekolah sehingga akan membebankan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. "Anak-anak yang bersekolah swasta tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil yang tidak bisa masuk sekolah negeri," kata Ketua DPD RI itu. Sementara untuk rencana pemberlakuan PPN terhadap sembako, ia menilai hal itu justru menghambat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena jika daya masyarakat turun maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara,” ujar LaNyalla. Ia menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain dalam membenahi sistem perpajakan melalui berbagai upaya kreatif dalam rangka mendorong penerimaan negara. "Pemerintah juga harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," ujar Ketua DPD RI LaNyalla.
Pengamat: Duet Prabowo-Puan Paling Mungkin Diwujudkan pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Igor Dirgantara menyatakan, duet Prabowo Subianto-Puan Maharani dinilai paling mungkin diwujudkan jika Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada Pilpres 2024. "Prabowo-Puan. Pasangan ini paling mungkin diwujudkan dan dinilai cocok karena faktor usia (tua-muda), jenis kelamin (pria-wanita), serta latar belakang militer-sipil," kata Igor, yang juga sebagai Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis. Namun, lanjut dia, dari duet tersebut belum bisa diprediksi mengenai siapa yang menjadi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Karena masing-masing punya kelebihan tersendiri untuk ditempatkan sebagai capres. "Salah satu kendala dari pasangan ini adalah pandangan bahwa PDIP sebagai parpol pemenang pemilu dengan 128 kursi di parlemen, apa mau memposisikan kandidatnya di posisi RI-2? Jawabannya tentu bisa mengingat elektabilitas Prabowo yang jauh lebih tinggi, begitu juga dengan pengalamannya," ujarnya. Menurut dia, bisa saja nanti dilakukan redefinisi ulang Perjanjian Batu Tulis. Dia menjelaskan jika Batu Tulis 2009 (jilid I) ada klausul bahwa Prabowo sebagai cawapres Megawati akan didukung oleh PDIP maju sebagai Capres 2014. Namun, hal itu akhirnya batal karena akhirnya PDIP mencalonkan Joko Widodo. "Maka kebalikannya, Batu Tulis 2024 (jilid II) juga bisa dibuat klausul bahwa jika Puan Maharani menjadi cawapres Prabowo di 2024, maka Gerindra gantian mendukung pencalonan Puan Maharani sebagai capres pada tahun 2029 berikutnya," tuturnya. Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman mengatakan, jika nantinya Prabowo jadi capres, maka Puan adalah pasangan duet yang ideal karena memiliki berbagai pengalaman di tingkat nasional. "Jika Pak Prabowo disiapkan jadi Capres maka Mbak Puan adalah pasangan yang pas untuk mendampingi sebagai Cawapresnya, usia Mbak Puan relatif muda namun sarat dengan pengalaman," tutur Arip. Puan dinilai punya pengalaman keberhasilan sebagai Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan saat ini menjabat Ketua DPR RI. "Jadi, walaupun berusia relatif muda namun sarat pengalaman eksekutif maupun legislatif," lanjut Arip. Ia pun menambahkan, tidak banyak tokoh nasional yang memiliki pengalaman lengkap di level nasional seperti Puan Maharani. "Apalagi menjadi Ketua DPR RI, harus memiliki kemampuan dan seni memimpin yang tinggi dan kami melihat Mbak Puan selalu terasa kehadirannya setiap saat sebagai pimpinan DPR RI," ucapnya. (mth)
Ketua DPD RI Kunjungi Bupati Ponorogo
Ponorogo, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersilaturahmi menemui Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di kantor bupati setempat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu. Dalam kunjungannya ke Kota Reog itu, mantan Ketua Umum Kadin Jatim tersebut, didampingi Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Rombongan disambut oleh Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, dan jajaran pejabat pemkab setempat. Dalam silaturahmi tersebut, senator asal Jawa Timur ini menegaskan kembali wacana DPD RI untuk melakukan amendemen ke-5 terhadap UUD 1945. Menurutnya, amendemen ke-5 dibutuhkan agar hak DPD sebagai jelmaan dari utusan daerah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden bisa pulih. "Kami selain keliling daerah juga keliling ke kampus-kampus menggaungkan wacana tersebut lewat seminar maupun FGD, sehingga para akademisi bisa ikut serta mendorong wacana tersebut," kata La Nyalla di sela silaturahmi. Bupati Ponorogo Sugiri menjamu tamunya tersebut dengan hidangan makan siang khas Ponorogo, di antaranya nasi tiwul dan bothok, beserta minuman dawet. Sebelum ke Ponorogo, La Nyalla juga sowan atau bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Di Pesantren Temboro itu, mantan Ketua Umum PSSI tersebut bertemu dengan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang juga sedang suluk ke Ponpes Al-Fatah Magetan. Keduanya kemudian saling bertukar cenderamata. La Nyalla memberikan cenderamata kain kiswah, sedangkan Helmi Hasan memberikan tongkat. (sws)
Dahsyat, Kemampuan Akademis Prof Dr Megawati
By Asyari Usman Medan, FNN - Setelah diberi gelar doktor kehormatan, Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) yang berkampus di Sentul, Kabupaten Bogor. Acara penobatan akan berlangsung Jumat, 11 Juni 2021. Akan sempurnalah kapasitas akademis beliau: Prof Dr Megawati Soekarnoputri. Unhan mengatakan mereka menerima seluruh karya ilmiah Megawati. Presiden kelima ini akan menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul "Kepemimpinan Strategis Pada Masa Kritis". Banyak yang merasa heran, terutama para netizen. Mereka mencibiri gelar profesor kehormatan itu. Padahal, untuk mendapatkan gelar ini Bu Mega “menulis” begitu banyak karya ilmiah. Salah satu yang viral adalah “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”. Ini tidak sembarangan. Beliau mengklaim telah melakukan penelitian kualitatif. Pendekatannya studi kasus. Membaca sepintas, karya ilmiah Bu Mega ini memang dahsyat. Di bagian “abstrak”-nya, Bu Mega mengatakan penelitian ini menggunakan kerangka teori Byman dan Pollack (2001) sebagai pisau analisis. Tulisan ini dihiasi kutipan kelas dunia. Untuk tulisan 16 halaman ini, Bu Mega mengutip 19 buku dan tulisan ilmiah plus tujuh undang-undang RI. Serius sekali. Bu Mega telah membaca banyak buku tentang ekonomi, politik, perbankan, bisnis, dll. Di bagian awal saja Bu Mega menunjukkan pemahaman yang luas dan dalam tentang krisis moneter 1997-1998 tempo hari. Intinya, lewat tulisan yang dimuat di Jurnal Pertahanan & Bela Negara, April 2021, Volume 11 Nomor 1, Megawati mengatakan bahwa kepemimpinan dia sebagai presiden 2001-2004 sangatlah hebat. Sebab, krisis yang melanda Indonesia datang dari berbagai arah (multidimensional). Dan krisis berat ini bisa dinavigasikannya dengan piawai. Membaca karya ilmiah ini, terlihat literasi Bu Mega sangat luas spektrumnya. Di bagian “Pendahuluan”, Bu Mega memberikan isyarat bahwa dia membaca berbagai analisis termasuk Kuncoro (2011), Basri (2011), Wirutomo (2003), Harahap (2018), Windiani (2017), Byman (1986), Fielder (1967), Avolio (2007), Larry Greiner (1972), Moleong (2008), Yin (2013), Lukman (2004). Bu Mega juga membaca tulisan Robert D Putnam (Universitas Harvard) yang berjudul “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. Artikel ini menyimpulkan bahwa persetujuan internasional baru akan didukung kalau memberikan keuntungan domestik. Megawati mengutip artikel 34 halaman yan terbit di jurnal International Organization ini untuk menjelaskan bahwa dia adalah presiden yang memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Tetapi, ada buku Putnam yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi politik Indonesia yang tidak dijadikan rujukan. Yaitu, “Making Democracy Work” (1993). Buku ini membahas soal “social capital” (modal sosial). Menurut buku ini, sukses demokrasi sangat bergantung pada “horizontal bonds” (ikatan horizontal) di tengah masyarakat. Intinya adalah “trust” (kepercayaan) antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti apa ikatan horizontal di negeri ini pada saat sekarang? Tentu kita semua bisa lihat sendiri. Rajut sosial sudah rusak berat gara-gara pemimpin yang tidak berkualitas. Padahal, kata Putnam, modal sosial yang kuat akan mendorong partisipasi publik yang tinggi dan juga menumbuhkan kemakmuran ekonomi. Nyatanya, aspek ini hancur-lebur. Megawati juga mengutip buku Barry Buzan “People, States and Fear” (1991). Dengan mengutip profesor hubungan internasional di London School of Economic ini, Bu Mega mau menjelaskan betapa beratnya ancaman keamanan dalam kategori militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial semasa dia menjadi presiden. Tapi, semua itu bisa diatasinya. Keren, bukan? Kemudian, dia juga mengutip Robinson & Rosser (1998) tentang utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 150 miliar USD yang ditinggalkan Orde Baru. Di sini, Mega mengklaim bahwa dia berhasil meminta penjadwalan ULN itu di forum Paris Club dan London Club. Padahal, penjadwalan ulang adalah formula yang akan disetujui oleh semua kreditur internasional. Sebab, semua pihak paham tentang kesulitan debitur mana pun untuk membayar utang yang jatuh tempo pada masa krisis. Paris Club dan London Club tak mungkin memaksa Indonesia membayar tepat waktu. Bahkan, tanpa perundingan pun pasti para kreditur akan menawarkan penjadwalan ulang (reschedule). Jadi, klaim Megawati ini tampaknya “patronizing”. Seolah orang lain tidak mengerti. Dikutip pula Dahuri & Samah (2019) tentang larangan impor, sebaliknya mendorong swadaya pangan. Dicantumkan pula Wuryandari (2008) tentang “sense of urgency” dan “sense of crisis” yang dia katakan tidak dimiliki oleh pemerintah sebelum dia menjadi presiden. Megawati juga mengklaim keberhasilan dalam reformasi peranan militer (TNI). Dia membanggakan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang disahkan semasa dia presiden. UU ini adalah bagian dari reformasi TNI yang “on going” (terus bergulir). Urusan reformasi TNI terlalu besar bagi Bu Mega untuk mengklaim seolah beliaulah yang menginisiasi perubahan itu. Harap diingat, reformasi TNI adalah desakan rakyat. Bukan desakan DPR, apalagi desakan presiden. Bu Mega juga menulis, “Masa kepemimpinan Megawati menorehkan tinta emas dalam penataan hubungan sipil-militer di Indonesia.” Klaim ini mengabaikan peranan Presiden Gus Dur. Kemudian, di bagian lain Megawati mengklaim langkah-langkah strategis dengan membentuk badan-badan yang di kemudian hari menjadi sangat penting. Termasuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dlsb. Ini pun klaim yang sifatnya “itu saya, ini saya, semuanya saya”. Bu Mega seharusnya paham bahwa proses reformasi yang diawali dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, pastilah akan berlanjut bertahun-tahun kemudian. Bahkan hingga sekarang pun reformasi masih belum tuntas. Artinya, pembentukan badan-badan itu hanyalah menunggu antrian prioritas agenda reformasi tsb. Cepat atau lambat pasti berlanjut ke situ. Kebetulan pembentukannya memang kondusif pada era Bu Mega. Dia tentu berperan. Tapi, mengklaim bahwa itu semua tak akan terlaksana tanpa “leadership” dia, bisa memicu rasa mual. Bagaimana pun juga, tulisan ilmiah ini menunjukkan Bu Mega memiliki kemampuan akademis yang dahsyat. Karena itu, ada baiknya Prof Dr Megawati aktif membimbing mahasiswa S3. Sayang sekali kalau ilmuwan sekaliber beliau ini tidak menularkan kapabilitasnya kepada para calon pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Wawasan Bu Mega yang begitu luas dengan literasi “high end” yang meyakinkan, sangat diperlukan oleh banyak kampus.[] Penulis wartawan senior FNN.co.id
Kapitra Minta Pimpinan KPK Abaikan Panggilan Komnas HAM Soal TWK ASN
Jakarta, FNN - Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan pimpinan lainnya untuk mengabaikan pemanggilan Komnas HAM soal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN. Kapitra, dalam rilisnya diterima di Jakarta Rabu, mengatakan permintaannya itu karena melihat langkah pemanggilan pimpinan KPK dalam polemik tersebut bukan kewenangan dari Komnas HAM. “Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya," kata dia. Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, menurut Kapitra terasa aneh kalau Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK. “Kewenangan Komnas HAM menurut UU nomor 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan genocide (pembantaian besar-besaran),” ucap Kapitra. Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa 8 Juni 2021. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ali menjelaskan, pihaknya hendak meminta penjelasan kepada Komnas HAM tentang pelanggaran apa yang dilakukan pimpinan KPK. "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali. (sws)
KPU Banjarmasin: Pemilih Antusias Ikuti PSU Pilkada Kalsel 2020
Banjarmasin, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin menyebutkan pemilih antusias mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan 2020 pasca putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang digelar Rabu ini. "Pantauan kami, ke TPS-TPS cukup antusias pemilih datang untuk mencoblos," ujar anggota KPU Kota Banjarmasin Syafruddin Akbar di Banjarmasin, Rabu. Dia menyatakan memantau di wilayah Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, di mana jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 29 TPS. "Rata-rata yang kami dapat laporan sejak pagi tadi antusias pemilih datang ke TPS cukup tinggi, moga berlanjut demikian hingga siang," ujarnya. Sebagaimana dinyatakan Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah sebelumnya, target pemilihan PSU Pilgub Kalsel di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebesar 79 persen. Jumlah TPS yang gelar PSU Pilgub Kalsel di Kota Banjarmasin, yakni di Banjarmasin Selatan sebanyak 301 TPS yang tersebar di 12 kelurahan. Adapun jumlah pemilih sebanyak 107.782 jiwa sesuai daftar pemilih tetap (DPT). Dari pantauan Antara di TPS 16 Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan dinyatakan hingga pukul 09.30 WITA sudah mencapai sekitar 200 pemilih datang menggunakan hak suaranya dari DPT di TPS itu sebanyak 495 jiwa. Sebagaimana diketahui, Pilkada Kalsel tahun 2020 sesuai putusan Mahkamah Konsitusi (MK) harus digelar PSU di tujuh kecamatan, yakni, lima kecamatan di Kabupaten, Astambul, Matraman, Martapura, Aluh-Aluh dan Sambungan Makmur. Kemudian, pada 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dan seluruh TPS di Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Di mana total TPS yang akan digelar pada 827 titik, dengan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 266.736 jiwa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Kalsel 2020 adalah, Paslon nomor urut 1, H Sahbirin Noor dan H Muhidin, Paslon nomor urut 2, Prof H Denny Indrayana dan H Difriadi Derajat. (sws)